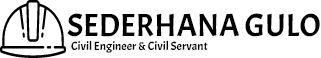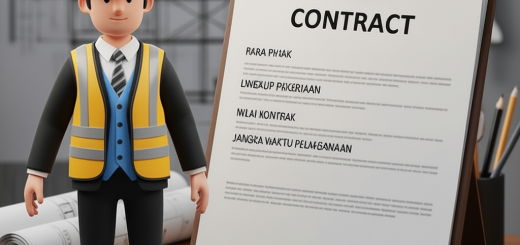Analisis Komprehensif Kontrak Konstruksi dan Administrasi Proyek: Perspektif Hukum dan Praktik di Indonesia

BAB I: PENDAHULUAN: MEMAHAMI KONTRAK DAN KONTRAK KONSTRUKSI
1.1. Definisi Perjanjian dan Kontrak menurut Hukum
Memahami esensi dari suatu perjanjian atau kontrak merupakan langkah fundamental sebelum mendalami aspek-aspek yang lebih spesifik dalam konteks industri konstruksi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, sebagai landasan hukum perdata umum, memberikan definisi dasar mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih”.1 Definisi ini, meskipun fundamental, seringkali dianggap belum sepenuhnya mencakup kompleksitas perjanjian modern, terutama karena terkesan hanya menyoroti aspek perjanjian sepihak.2
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, pandangan para ahli hukum menjadi relevan. Garner (2004) mendefinisikan kontrak sebagai “suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan hak dan kewajiban yang dapat diberlakukan atau dikenal dalam hukum” atau “janji atau serangkaian janji-janji oleh para pihak untuk suatu transaksi, yang dapat diberlakukan atau dikenal dalam hukum dan perundangan yang berlaku”.3 Definisi ini menekankan pada aspek keberlakuan hukum dan timbulnya hak serta kewajiban. Senada dengan itu, Martin dan Law (2006) menyatakan bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian yang mengikat secara hukum,” yang timbul dari adanya “penawaran dan persetujuan,” namun memerlukan pemenuhan persyaratan lain agar mengikat secara hukum.3 Chow (2006) juga menegaskan bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum dan terjadi ketika salah satu pihak menyetujui penawaran yang dibuat oleh pihak lain dan memenuhi persyaratan”.3
Dalam konteks Indonesia, Lukman Ali et al (1994) memberikan definisi yang lebih luas, yaitu “perjanjian antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan”.3 Sementara itu, Tay & Tang (2004) secara ringkas menyatakan bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terkait”.3 Ahli hukum Indonesia seperti Soebekti mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.2 Mariam Darus Badrulzaman lebih lanjut mengartikannya sebagai “perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu”.2
Istilah “perjanjian” dan “kontrak” seringkali digunakan secara bergantian. Namun, beberapa pandangan, seperti yang diungkapkan Soebekti, menyatakan bahwa perkataan “kontrak” memiliki cakupan yang lebih sempit karena lebih sering ditujukan kepada perjanjian yang dibuat secara tertulis.2 Meskipun demikian, dalam praktik dan berbagai literatur hukum, kedua istilah ini kerap dianggap sinonim.
Keterbatasan definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang cenderung menyoroti aspek unilateral (sepihak) dari suatu perjanjian menunjukkan bahwa pemahaman kontrak dalam konteks modern, khususnya dalam transaksi bisnis dan konstruksi yang kompleks, memerlukan rujukan pada doktrin dan pandangan para ahli. Pasal tersebut dirumuskan pada abad ke-19, sementara praktik kontrak kontemporer didominasi oleh perjanjian timbal balik (bilateral) di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Para ahli hukum modern secara konsisten menekankan aspek “dua pihak atau lebih” dan “saling mengikatkan diri” atau “hak dan kewajiban timbal balik”.2 Hal ini mengindikasikan adanya evolusi pemahaman dan kebutuhan akan interpretasi yang lebih luas agar definisi tersebut tetap relevan dengan dinamika transaksi saat ini. Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu kontrak, kejelasan mengenai sifat hubungan para pihak, apakah sepihak atau timbal balik, menjadi sangat penting untuk menghindari potensi ambiguitas di kemudian hari. Penekanan pada aspek “mengikat secara hukum” dan “dapat diberlakukan” dalam berbagai definisi tersebut menggarisbawahi konsekuensi yuridis yang melekat pada setiap kontrak yang sah.
1.2. Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan Akibat Hukumnya (Pasal 1338 KUHPerdata)
Legalitas dan kekuatan mengikat suatu perjanjian di Indonesia ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini merupakan fondasi bagi setiap kontrak dan ketidakpatuhan terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Terdapat empat syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah 1:
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: Para pihak harus mencapai konsensus atau kesepakatan kehendak yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, yang umumnya berarti telah dewasa (berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.5
- Suatu hal tertentu: Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan diperbolehkan oleh hukum. Ini merujuk pada prestasi yang diperjanjikan.
- Suatu sebab yang halal (causa yang legal): Tujuan atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.4
Kedua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek atau para pihak yang membuat perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Artinya, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat sampai ada pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan kepada pengadilan.1 Sebaliknya, dua syarat terakhir (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri. Pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege). Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak memiliki akibat hukum.1 Pemahaman akan perbedaan konsekuensi ini sangat krusial dalam menentukan strategi penyelesaian sengketa. Jika suatu kontrak batal demi hukum, maka tidak pernah ada hubungan hukum yang terbentuk. Namun, jika kontrak tersebut dapat dibatalkan, salah satu pihak harus mengambil tindakan aktif untuk meminta pembatalannya.
Setelah suatu perjanjian dibuat secara sah, Pasal 1338 KUHPerdata mengatur mengenai akibat hukumnya.1 Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Prinsip ini dikenal dengan adagium Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdata mengamanatkan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Prinsip itikad baik ini menuntut agar pelaksanaan kontrak dilakukan dengan kejujuran, kepatutan, dan memperhatikan kepentingan pihak lain, melampaui sekadar pemenuhan klausul-klausul yang tertulis secara literal.
Selain itu, terdapat asas-asas hukum perjanjian lain yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, dan asas kepribadian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.1 Meskipun KUHPerdata memberikan kebebasan berkontrak yang luas, kebebasan ini tidaklah absolut. Ia dibatasi oleh syarat “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dipertegas oleh Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang perjanjian dengan sebab yang dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum.7 Pembatasan ini, ditambah dengan kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik, menciptakan keseimbangan antara otonomi para pihak dalam berkontrak dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta nilai-nilai moralitas. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi harus memastikan bahwa tujuan dan isi kontrak mereka tidak hanya menguntungkan secara komersial tetapi juga selaras dengan kerangka hukum, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku. Setiap klausul yang ambigu atau berpotensi melanggar ketentuan ini dapat menjadi dasar timbulnya sengketa atau bahkan pembatalan kontrak.
1.3. Definisi, Karakteristik, dan Unsur-Unsur Kontrak Konstruksi
Setelah memahami konsep perjanjian secara umum, fokus beralih pada kontrak konstruksi yang memiliki kekhususan tersendiri. Garner mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai “suatu kontrak yang memuat spesifikasi untuk suatu pembangunan proyek konstruksi”.3 Definisi ini menyoroti aspek spesifikasi teknis yang menjadi ciri khas kontrak jenis ini. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (meskipun telah dicabut, definisinya masih relevan untuk konteks historis) menyebutkan kontrak konstruksi sebagai “perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan penggunaan utama”.3
Definisi yang paling otoritatif saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 angka 8 UU tersebut menyatakan bahwa, “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”.8 Definisi ini menekankan dua hal penting: pertama, kontrak konstruksi terdiri dari “keseluruhan dokumen,” bukan hanya lembar perjanjian utama; dan kedua, kontrak tersebut “mengatur hubungan hukum” antara para pihak.
Para ahli seperti Seng Hansen dan Sarwono Hardjomuljadi menggarisbawahi bahwa kontrak konstruksi adalah jenis kontrak yang rumit, unik, dipengaruhi oleh banyak faktor, dan berbeda secara signifikan dari kontrak-kontrak komersial lainnya.2 Kompleksitas ini timbul dari berbagai faktor, antara lain durasi proyek yang umumnya panjang, keterlibatan beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda, tingkat ketidakpastian kondisi lapangan yang tinggi, potensi perubahan desain selama pelaksanaan, serta risiko teknis dan finansial yang signifikan. Kontrak konstruksi tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek teknis, administrasi, keuangan, perpajakan, hingga sosial ekonomi, dan seringkali mengikuti format standar tertentu.10 Dokumen kontrak itu sendiri menjadi acuan utama dan sangat penting bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.2
Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam suatu kontrak konstruksi, sebagaimana diindikasikan dalam regulasi terdahulu (PP No. 29 Tahun 2000, yang kini digantikan oleh PP No. 22 Tahun 2020), meliputi adanya subjek (yaitu Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa), adanya objek (yaitu bangunan atau hasil pekerjaan konstruksi), dan adanya dokumen yang secara formal mengatur hubungan hukum di antara para subjek tersebut.12
Penekanan dalam UU No. 2 Tahun 2017 pada frasa “keseluruhan dokumen kontrak” memiliki implikasi yang besar dalam interpretasi dan administrasi kontrak. Ini berarti bahwa kewajiban kontraktual tidak hanya bersumber dari lembar perjanjian pokok, tetapi juga dari berbagai lampiran seperti syarat-syarat umum dan khusus kontrak (General and Special Conditions of Contract), gambar-gambar rencana, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga (Bill of Quantities), serta dokumen-dokumen lain yang disepakati menjadi bagian dari kontrak.3 Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Pasal 76 secara eksplisit merinci dokumen-dokumen minimum yang membentuk satu kesatuan kontrak kerja konstruksi.13 Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh set dokumen kontrak menjadi krusial. Para praktisi di bidang konstruksi dituntut untuk cermat dalam menyusun dan mereview keseluruhan dokumen tersebut guna memastikan konsistensi dan menghindari potensi konflik antar dokumen, yang seringkali menjadi pemicu sengketa.
Kontrak konstruksi dalam sistem hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai kontrak innominaat, yaitu jenis perjanjian yang namanya tidak secara spesifik diatur dalam KUHPerdata.10 Keberadaan kontrak innominaat menunjukkan fleksibilitas hukum perdata Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan jenis-jenis kontrak baru seiring dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata, semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tetap tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Buku Ketiga KUHPerdata mengenai Perikatan.10 Ini berarti, meskipun terdapat undang-undang khusus yang mengatur jasa konstruksi (seperti UU No. 2 Tahun 2017), prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan asas-asas perjanjian lainnya tetap berlaku sebagai landasan, kecuali jika diatur secara khusus dan berbeda oleh undang-undang spesifik tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap UU Jasa Konstruksi harus senantiasa didasari oleh pemahaman yang kokoh terhadap prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dalam KUHPerdata.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbandingan definisi kontrak secara umum dan kontrak konstruksi dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1.1: Perbandingan Definisi Kontrak dan Kontrak Konstruksi
| Istilah | Sumber | Definisi Inti | Poin Kunci |
| Kontrak Umum | KUHPerdata Pasal 1313 | Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. | Fokus pada tindakan mengikatkan diri, cenderung unilateral. |
| Ahli (mis. Garner, Martin & Law) | Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak & kewajiban yang dapat diberlakukan hukum; hasil dari penawaran & penerimaan. | Mengikat secara hukum, timbal balik, dapat dipaksakan, memerlukan pemenuhan syarat. | |
| Kontrak Konstruksi | UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 1(8) | Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. | Keseluruhan dokumen, hubungan hukum spesifik, para pihak tertentu (Pengguna & Penyedia Jasa). |
| Ahli (mis. Sarwono H., Seng Hansen) | Kontrak yang rumit, unik, memuat spesifikasi teknis, dipengaruhi banyak faktor, berbeda dari kontrak komersial lain. | Kompleks, spesifik teknis, melibatkan banyak aspek (teknis, hukum, finansial, dll.). | |
| PP No. 24 Tahun 2005 (historis) | Perikatan khusus untuk konstruksi aset atau kombinasi aset yang saling terkait dalam hal rancangan, teknologi, fungsi, atau tujuan utama. | Fokus pada tujuan konstruksi aset fisik, keterkaitan elemen desain & fungsi. |
Tabel ini membantu membedakan konsep kontrak secara umum dengan kekhususan yang melekat pada kontrak konstruksi. Dengan menyandingkan definisi dari berbagai sumber, baik hukum positif maupun pandangan ahli, dapat terlihat evolusi dan nuansa pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua jenis kontrak tersebut. Poin kunci menyoroti elemen-elemen esensial dari masing-masing definisi, yang memudahkan pemahaman inti, sejalan dengan tujuan Modul 1 mata kuliah ini yang dimulai dari pemahaman umum sebelum memasuki ranah spesifik kontrak konstruksi.3
BAB II: LANDASAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA
Penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum ini esensial bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri konstruksi, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas. Dua pilar utama regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020.
2.1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Ruang Lingkup dan Pokok-Pokok Pengaturan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK No. 2/2017) hadir menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Latar belakang pembentukan UUJK No. 2/2017 adalah karena regulasi sebelumnya dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan akan tata kelola yang baik (good governance) serta belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang semakin kompleks.8
Secara definitif, UUJK No. 2/2017 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Jasa Konstruksi sebagai layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.8 Lebih lanjut, Konsultansi Konstruksi diartikan sebagai layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan (Pasal 1 angka 2).8 Sementara itu, Pekerjaan Konstruksi mencakup keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pasal 1 angka 3).9
Tujuan utama dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UUJK No. 2/2017 antara lain adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa konstruksi guna mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, dan berdaya saing tinggi, serta menghasilkan Jasa Konstruksi yang berkualitas. Selain itu, UU ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.8
Pemerintah Pusat, menurut Pasal 5 UUJK No. 2/2017, memegang tanggung jawab yang signifikan, termasuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, serta mengembangkan standar material, peralatan, dan inovasi teknologi konstruksi.8
Salah satu aspek sentral yang diatur dalam UUJK No. 2/2017 adalah Kontrak Kerja Konstruksi. Sebagaimana telah disebutkan, Pasal 1 angka 8 mendefinisikannya sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.8 Pasal 47 UUJK No. 2/2017 menetapkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai para pihak yang terlibat, rumusan pekerjaan (lingkup, nilai, jangka waktu), masa pertanggungan (jaminan), hak dan kewajiban para pihak, penggunaan tenaga kerja konstruksi, cara pembayaran, ketentuan mengenai cidera janji (wanprestasi), mekanisme penyelesaian sengketa, pemutusan kontrak, keadaan kahar (force majeure), tanggung jawab atas kegagalan bangunan, aspek pelindungan pekerja, aspek lingkungan hidup, pemberian insentif (jika ada), dan bahasa kontrak yang digunakan.8
UUJK No. 2/2017 juga memberikan perhatian khusus pada Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK). Pasal 1 angka 9 mendefinisikan SMKK sebagai pedoman teknis terkait keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.8 Pasal 59 secara tegas mewajibkan pemenuhan SMKK dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi.8 Kewajiban ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya aspek non-teknis dalam keberhasilan proyek konstruksi, yang mungkin kurang mendapatkan penekanan pada regulasi sebelumnya. Penerapan SMKK yang komprehensif diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja, dampak lingkungan negatif, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas serta keberlanjutan hasil konstruksi. Kegagalan dalam memenuhi SMKK dapat berujung pada tanggung jawab hukum atas Kegagalan Bangunan.
Hak dan kewajiban Pengguna Jasa serta Penyedia Jasa diatur secara lebih rinci dalam Pasal 51 dan 52 UUJK No. 2/2017.8 Keseimbangan hak dan kewajiban ini menjadi landasan bagi terciptanya hubungan kontraktual yang adil dan setara.
Aspek Kegagalan Bangunan juga mendapatkan porsi pengaturan yang signifikan (Pasal 1 angka 12, Pasal 60-68).8 UU ini mengatur mengenai tanggung jawab Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa jika terjadi kegagalan bangunan, termasuk mekanisme penentuan penyebab dan jangka waktu pertanggungjawaban.
Terakhir, terkait Penyelesaian Sengketa, Pasal 88 UUJK No. 2/2017 mengatur bahwa sengketa yang timbul dalam Kontrak Kerja Konstruksi diupayakan penyelesaiannya melalui tahap musyawarah untuk mufakat.8 Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) atau melalui pengadilan (litigasi).14 Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa ini menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan jalur yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan hanya bergantung pada proses peradilan formal, sejalan dengan semangat yang diusung oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.15 Keberagaman pilihan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih cara penyelesaian yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa, dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya, dan potensi untuk menjaga hubungan bisnis di masa depan.
2.2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020: Ketentuan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi
Sebagai amanat dari UUJK No. 2/2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP No. 22/2020).13 Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional yang lebih detail dan teknis guna menjamin implementasi UUJK No. 2/2017 dapat berjalan efektif.
PP No. 22/2020 merinci berbagai aspek, di antaranya:
- Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Mengatur pembagian peran dalam pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi.
- Jenis Usaha Jasa Konstruksi: Mengelaborasi lebih lanjut mengenai jenis usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, termasuk sifat dan klasifikasi usaha yang lebih detail.13
- Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK): Pasal 1 angka 11 PP No. 22/2020 menegaskan kembali definisi SMKK sebagai pedoman teknis yang harus dipatuhi.13
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi: Mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan dan akuntabel (Pasal 1 angka 22).13
- Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi: Memberikan perhatian pada pengelolaan rantai pasok material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi (Pasal 1 angka 24).13
Salah satu bagian paling krusial dalam PP No. 22/2020 adalah pengaturan mengenai Pemilihan dan Penetapan Penyedia Jasa (Pasal 60-74).13 Untuk pengadaan yang menggunakan pendanaan negara (APBN/APBD), PP ini menetapkan prinsip-prinsip pemilihan yang ketat, sistem seleksi yang meliputi penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran, serta berbagai metode pemilihan seperti tender/seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan pengadaan melalui katalog elektronik (e-katalog). Penekanan pada standardisasi dan prosedur dalam pemilihan Penyedia Jasa ini, terutama untuk proyek pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di sektor konstruksi. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam proyek-proyek yang didanai oleh negara, karena setiap penyimpangan dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif.
Selanjutnya, PP No. 22/2020 juga mengatur secara komprehensif mengenai Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 75-82).13 Ditegaskan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi tunduk pada hukum Indonesia. Pasal 76 secara rinci menyebutkan dokumen-dokumen minimum yang harus menjadi bagian dari Kontrak Kerja Konstruksi, meliputi Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Dokumen Pengguna Jasa (yang mencakup spesifikasi teknis, gambar rencana, daftar kuantitas/keluaran, dan harga), Proposal atau Penawaran dari Penyedia Jasa, Berita Acara Rapat klarifikasi dan negosiasi, Surat Pernyataan dari Pengguna Jasa mengenai penerimaan penawaran, serta Surat Pernyataan dari Penyedia Jasa mengenai kesediaan untuk melaksanakan pekerjaan. Kelengkapan dokumen ini sangat vital untuk memastikan kejelasan dan menghindari ambiguitas yang dapat memicu sengketa.
PP No. 22/2020 juga memperkenalkan atau merinci lebih lanjut ketentuan mengenai insentif (Pasal 78).13 Insentif dapat diberikan kepada Penyedia Jasa yang berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih awal dari jadwal kontrak dengan tetap menjaga standar kualitas yang telah disepakati. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong kinerja yang lebih unggul dari Penyedia Jasa, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban minimum. Pengguna Jasa dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan klausul insentif dalam kontrak sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek, namun hal ini harus direncanakan sejak tahap persiapan pengadaan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, PP ini mengatur mengenai kemungkinan dilakukannya peninjauan oleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 79), terutama untuk kontrak dengan teknologi tinggi, risiko tinggi, atau peralatan yang dirancang khusus, serta wajib untuk Kontrak Kerja Konstruksi terintegrasi.13 PP No. 22/2020 juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan sistem penyampaian pekerjaan (construction delivery system), sistem pembayaran, dan sistem perhitungan hasil pekerjaan (Pasal 80-82) 13, yang memungkinkan para pihak untuk menyusun kontrak yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik proyek.
Mengenai Tanggung Jawab atas Kegagalan Bangunan (Pasal 85-90) 13, PP No. 22/2020 mengelaborasi peran Penilai Ahli dalam menentukan penyebab kegagalan bangunan, jangka waktu pertanggungjawaban para pihak, lingkup tanggung jawab (termasuk penggantian atau perbaikan), kemungkinan pengalihan tanggung jawab melalui mekanisme asuransi, serta ketentuan mengenai pemberian ganti rugi kepada pihak yang terdampak.
Terakhir, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 44-59) 13 diatur lebih detail, mencakup pelaksanaan pekerjaan secara mandiri atau melalui perjanjian Jasa Konstruksi. Ditekankan kembali kewajiban untuk memenuhi SMKK, menggunakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat, penerapan standar remunerasi minimum untuk tenaga ahli, pemenuhan tanggung jawab profesional, prioritas penggunaan sumber daya konstruksi dalam negeri, penerapan inovasi teknologi, dan pertimbangan aspek risiko dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi. PP ini juga memberikan rincian pelaksanaan untuk setiap jenis layanan Konsultansi Konstruksi (Pengkajian, Perencanaan, Perancangan, Pengawasan, dan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi) serta untuk setiap tahapan Pekerjaan Konstruksi (Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembongkaran, dan Pembangunan Kembali).
BAB III: PARA PIHAK DALAM KONTRAK KONSTRUKSI: PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Kontrak konstruksi melibatkan interaksi kompleks antara berbagai pihak, masing-masing dengan peran, hak, dan kewajiban yang spesifik. Pemahaman yang jelas mengenai kedudukan masing-masing pihak sangat krusial untuk kelancaran pelaksanaan proyek dan administrasi kontrak yang efektif. UUJK No. 2/2017 dan PP No. 22/2020 menjadi landasan utama dalam mendefinisikan hubungan ini.
3.1. Pengguna Jasa (Pemberi Kerja/Pemilik Proyek)
Pengguna Jasa, sering disebut juga sebagai Pemberi Kerja atau Pemilik Proyek, adalah pihak yang memiliki kebutuhan akan suatu bangunan atau infrastruktur dan menggunakan layanan Jasa Konstruksi untuk mewujudkannya. Dalam UUJK No. 2/2017 Pasal 1 angka 6, Pengguna Jasa didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.8 Dalam struktur kontrak konstruksi, Pengguna Jasa umumnya bertindak sebagai Pihak Kesatu.18
Hak Pengguna Jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJK No. 2/2017, meliputi:
- Memperoleh hasil layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang ditunjuk (misalnya, konsultan pengawas).
- Memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kemajuan dan pelaksanaan pekerjaan.
- Menahan sebagian pembayaran sebagai jaminan atas pemenuhan mutu pekerjaan atau untuk keperluan retensi selama masa pemeliharaan.
Kewajiban Pengguna Jasa, sesuai Pasal 52 UUJK No. 2/2017, mencakup:
- Memastikan kelayakan finansial proyek, termasuk ketersediaan dana untuk pembayaran layanan Jasa Konstruksi.
- Menyediakan lahan atau lokasi kerja yang siap untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- Melakukan pembayaran biaya layanan Jasa Konstruksi secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- Memberikan informasi, data, dan fasilitas lain yang diperlukan oleh Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- Memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK) dalam lingkup tanggung jawabnya.
Pengguna Jasa juga turut bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan apabila kegagalan tersebut terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak Pengguna Jasa, misalnya akibat dari perencanaan yang cacat (jika perencanaan dilakukan sendiri oleh Pengguna Jasa) atau instruksi yang salah selama pelaksanaan.8 Salah satu kewajiban Pengguna Jasa yang fundamental dan seringkali menjadi titik kritis adalah memastikan kelayakan finansial proyek dan melakukan pembayaran tepat waktu. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran ini merupakan salah satu pemicu utama klaim dan sengketa dari pihak Penyedia Jasa.19 Oleh karena itu, transparansi mengenai sumber pendanaan dan komitmen pembayaran yang kuat dari Pengguna Jasa menjadi sangat penting. Sebaliknya, Penyedia Jasa juga disarankan untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terkait kemampuan finansial Pengguna Jasa sebelum terikat dalam kontrak.
3.2. Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana)
Penyedia Jasa, yang dalam konteks pekerjaan fisik konstruksi lebih dikenal sebagai Kontraktor Pelaksana, adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi. UUJK No. 2/2017 Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Penyedia Jasa sebagai Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.8 Dalam kontrak, Penyedia Jasa bertindak sebagai Pihak Kedua.18
Hak Penyedia Jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJK No. 2/2017, antara lain:
- Memperoleh imbalan jasa atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan progres dan ketentuan kontrak secara tepat waktu.
- Memperoleh informasi, data, dan fasilitas yang diperlukan dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- Mengajukan klaim atas tambahan biaya dan/atau waktu jika terjadi perubahan pekerjaan, keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa, atau kondisi lain yang diatur dalam kontrak.
- Menghentikan pekerjaan jika Pengguna Jasa terbukti tidak memenuhi kewajiban esensialnya, seperti kewajiban pembayaran.
Kewajiban Penyedia Jasa, sesuai Pasal 52 UUJK No. 2/2017, mencakup:
- Melaksanakan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan lingkup, spesifikasi, gambar, dan ketentuan lain yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- Menggunakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan yang sesuai.
- Menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.
- Memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK) selama pelaksanaan pekerjaan.
Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh atas metode pelaksanaan pekerjaan dan kualitas hasil konstruksi. Jika terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau penggantian.8 Kewajiban Penyedia Jasa untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang “tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu” merupakan inti dari kinerja kontraktual mereka. Kegagalan dalam memenuhi salah satu dari ketiga aspek fundamental ini dapat memicu berbagai konsekuensi, mulai dari pengenaan denda keterlambatan, klaim cacat mutu dari Pengguna Jasa, hingga yang paling ekstrem adalah pemutusan kontrak. Oleh karena itu, kemampuan manajemen proyek yang efektif, meliputi perencanaan yang matang, pengendalian biaya yang cermat, pengawasan mutu yang ketat, dan manajemen waktu yang presisi, menjadi sangat krusial bagi Penyedia Jasa untuk dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya dan menghindari potensi sanksi atau kerugian.
3.3. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi (Enjinir/Pengawas/Manajemen Konstruksi)
Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, yang dalam Modul 1 mata kuliah ini sering disebut dengan istilah “Enjinir” 3, merujuk pada pelaku usaha yang menyediakan layanan keahlian khusus dalam berbagai tahapan proyek konstruksi. Peran mereka sangat vital, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan. UUJK No. 2/2017 dan PP No. 22/2020 mengkategorikan layanan Konsultansi Konstruksi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi.8
Dalam skema kontrak tradisional, Enjinir (khususnya Konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi) bertindak sebagai wakil dan penasihat ahli bagi Pengguna Jasa. Mereka ditugaskan untuk melaksanakan sebagian fungsi Pengguna Jasa dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan kontrak atas nama Pengguna Jasa.3 Penting untuk dicatat bahwa umumnya tidak terdapat ikatan kontrak langsung antara Kontraktor Pelaksana dengan Enjinir; hubungan kontrak Enjinir adalah dengan Pengguna Jasa melalui Perjanjian Pemberian Jasa Konsultansi Profesional.3
PP No. 22/2020 Pasal 50 merinci tugas Konsultan Pengawas, yang meliputi 13:
- Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.
- Melakukan pengawasan secara harian terhadap mutu proses pelaksanaan dan mutu hasil pekerjaan konstruksi.
- Mengawasi penerapan aspek keselamatan konstruksi di lapangan.
- Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa mengenai kemajuan dan kualitas pekerjaan. Konsultan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kontrak atau standar keselamatan.
Sementara itu, tugas Konsultan Manajemen Konstruksi, sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 51, mencakup spektrum yang lebih luas, meliputi 13:
- Manajemen proyek secara keseluruhan.
- Manajemen pelaksanaan konstruksi.
- Manajemen mutu.
- Manajemen keselamatan konstruksi. Kegiatan ini meliputi seluruh siklus proyek, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, hingga tahap pengakhiran proyek. Ini juga mencakup pengendalian biaya, jadwal dan waktu pelaksanaan, administrasi proyek, pengendalian pelaksanaan kontrak, pengendalian mutu konstruksi, dan pengendalian keselamatan konstruksi.
Meskipun Modul 1 3 menyatakan bahwa Enjinir tidak memiliki ikatan kontrak langsung dengan Kontraktor, keputusan dan tindakan yang diambil oleh Enjinir (misalnya dalam menyetujui metode kerja, menilai kualitas pekerjaan, memberikan persetujuan atas klaim, atau mengeluarkan instruksi perubahan) memiliki dampak hukum dan finansial yang sangat signifikan bagi Kontraktor. Enjinir, dalam kapasitasnya sebagai wakil Pengguna Jasa, memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan berbagai persetujuan.13 Jika Enjinir, misalnya, terlambat dalam memberikan persetujuan yang krusial, melakukan kesalahan dalam penilaian pekerjaan, atau mengeluarkan instruksi yang merugikan dan di luar lingkup kontrak, Kontraktor dapat mengajukan klaim terhadap Pengguna Jasa, karena Enjinir bertindak atas nama dan untuk kepentingan Pengguna Jasa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum tidak langsung namun memiliki konsekuensi yang kuat antara Kontraktor dan Enjinir. Oleh karena itu, baik Kontraktor maupun Pengguna Jasa harus memahami dengan baik peran, batasan kewenangan, dan standar profesionalisme yang diharapkan dari Enjinir sebagaimana diatur dalam kontrak. Komunikasi yang jelas dan dokumentasi yang lengkap atas setiap interaksi dan keputusan yang melibatkan Enjinir menjadi sangat esensial. Pengguna Jasa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Enjinir yang ditunjuk memiliki kompetensi yang memadai dan bertindak secara profesional dan imparsial.
PP No. 22/2020 13 memberikan rincian tugas yang lebih spesifik untuk Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen Konstruksi dibandingkan dengan UU No. 2 Tahun 2017 yang lebih bersifat umum.8 Detail ini, seperti evaluasi rencana mutu, pengawasan harian, pemeriksaan material, hingga penyiapan laporan 20, membantu memperjelas ekspektasi dan lingkup tanggung jawab konsultan dalam praktik. Oleh karena itu, dalam merumuskan kontrak jasa konsultansi, lingkup layanan Konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi sebaiknya dirumuskan secara jelas dengan merujuk pada detail tugas yang tercantum dalam PP No. 22/2020 untuk menghindari potensi tumpang tindih tanggung jawab atau adanya area abu-abu yang tidak terkelola.
3.4. Hubungan Hukum Antar Para Pihak
Struktur hubungan hukum antar para pihak dalam kontrak konstruksi umumnya terdiri dari beberapa lapis. Hubungan kontraktual utama terjalin antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana), yang diikat oleh dokumen Kontrak Kerja Konstruksi. Di sisi lain, Pengguna Jasa juga memiliki hubungan kontraktual dengan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi (Enjinir), yang diatur dalam Perjanjian Pemberian Jasa Konsultansi Profesional.3
Dalam skema tradisional, tidak terdapat ikatan kontrak secara langsung antara Kontraktor Pelaksana dengan Enjinir.3 Enjinir bertindak sebagai perpanjangan tangan atau agen dari Pengguna Jasa. Pemahaman terhadap struktur hubungan ini sangat penting karena akan menentukan alur komunikasi resmi, pembagian tanggung jawab, dan kepada siapa suatu klaim atau tuntutan hukum dapat diajukan. Sebagai contoh, jika Kontraktor merasa dirugikan oleh keputusan Enjinir, klaim tersebut umumnya diajukan kepada Pengguna Jasa, bukan langsung kepada Enjinir, karena Enjinir bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil Pengguna Jasa.
Meskipun tidak ada hubungan kontrak langsung, interaksi sehari-hari antara Kontraktor Pelaksana dan Enjinir (khususnya Konsultan Pengawas) di lapangan sangat intens dan krusial bagi kelancaran pelaksanaan proyek. Koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan pemahaman yang sama terhadap ketentuan kontrak menjadi kunci keberhasilan.
Salah satu tujuan utama dari UUJK No. 2/2017 dan PP No. 22/2020 adalah untuk menjamin adanya kesetaraan kedudukan (gelijkwaardigheid) antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi.8 Prinsip kesetaraan ini penting untuk mencegah adanya pihak yang memiliki posisi tawar yang terlalu dominan sehingga dapat memaksakan klausul-klausul yang merugikan pihak lain.
Namun demikian, dalam praktik, seringkali muncul potensi konflik kepentingan bagi Enjinir. Sebagai pihak yang ditunjuk dan dibayar oleh Pengguna Jasa, Enjinir diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional dalam menilai kualitas pekerjaan Kontraktor, memberikan persetujuan pembayaran, dan bahkan terkadang menilai validitas klaim yang diajukan oleh Kontraktor. Apabila Enjinir dianggap terlalu memihak kepada Pengguna Jasa dan mengabaikan hak-hak Kontraktor yang sah, hal ini dapat memicu timbulnya sengketa. Sebaliknya, jika Enjinir terlalu longgar dalam pengawasan, kualitas hasil pekerjaan dapat terancam, yang pada akhirnya merugikan Pengguna Jasa. Oleh karena itu, pentingnya klausul kontrak yang jelas mengenai peran, kewenangan, standar profesionalisme, dan independensi Enjinir tidak dapat diabaikan. Penggunaan mekanisme seperti Dewan Sengketa (Dispute Board) sejak awal proyek dapat menjadi salah satu alternatif untuk menengahi perbedaan pendapat terkait keputusan Enjinir sebelum berkembang menjadi sengketa formal.
Berikut adalah tabel ringkasan mengenai hak dan kewajiban utama para pihak dalam kontrak konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
Tabel 3.1: Hak dan Kewajiban Utama Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi (Berdasarkan UU No. 2/2017 & PP No. 22/2020)
| Pihak | Hak Utama | Kewajiban Utama | Rujukan Pasal (Contoh) |
| Pengguna Jasa | Memperoleh hasil Jasa Konstruksi sesuai Kontrak; Mengawasi pelaksanaan; Mendapatkan informasi; Menahan pembayaran (jaminan mutu). | Memastikan kelayakan finansial; Menyediakan lahan; Membayar tepat waktu; Memberikan informasi & fasilitas; Memenuhi SMKK. | UU 2/2017 Pasal 51, 52 |
| Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana) | Memperoleh imbalan jasa tepat waktu; Memperoleh informasi & fasilitas; Mengajukan klaim; Menghentikan pekerjaan (jika Pengguna Jasa wanprestasi). | Melaksanakan layanan sesuai Kontrak; Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat; Menyerahkan hasil tepat biaya, mutu, waktu; Memenuhi SMKK. | UU 2/2017 Pasal 51, 52 |
| Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan Pengawas) | Memperoleh imbalan jasa sesuai kontrak konsultansi. | Evaluasi & setujui rencana mutu & keselamatan; Awasi mutu proses & hasil; Awasi penerapan keselamatan; Bertanggung jawab atas hasil pengawasan; Lapor berkala ke Pengguna Jasa; Memberi izin/menghentikan pekerjaan. | PP 22/2020 Pasal 50; UU 2/2017 Pasal 52 (secara umum) |
| Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi (Manajemen Konstruksi) | Memperoleh imbalan jasa sesuai kontrak konsultansi. | Manajemen proyek, konstruksi, mutu, keselamatan; Pengendalian biaya, jadwal, administrasi, kontrak, mutu, keselamatan; dari tahap desain hingga selesai konstruksi. | PP 22/2020 Pasal 51; UU 2/2017 Pasal 52 (secara umum) |
Tabel ini menyajikan ringkasan terstruktur yang memudahkan pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur interaksi dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan proyek konstruksi di Indonesia, sejalan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 1 yang menuntut kemampuan analisis terhadap peran para pihak.3
BAB IV: ADMINISTRASI KONTRAK KONSTRUKSI: ESENSI DAN IMPLEMENTASI
Administrasi kontrak merupakan aspek fundamental dalam manajemen proyek konstruksi. Jauh dari sekadar aktivitas klerikal atau pengarsipan dokumen, administrasi kontrak yang efektif adalah sebuah fungsi manajerial strategis yang berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan proyek, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta pengelolaan risiko yang mungkin timbul selama siklus hidup kontrak.
4.1. Definisi, Maksud, dan Tujuan Administrasi Kontrak/Proyek
Modul 1 mata kuliah ini mendefinisikan administrasi kontrak dalam pengertian yang luas sebagai “seni mengelola aspek yang terlihat dan tidak terlihat dari suatu proyek”.3 Pengertian ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengaturan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal, pemanfaatan peralatan dan bahan secara efisien, pemahaman mendalam terhadap masalah teknis dan desain, hingga pemeliharaan hubungan kerja yang harmonis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pengguna Jasa, perwakilannya (Enjinir), dan Kontraktor pelaksana proyek.3 Sumber lain, seperti yang dikutip dalam 18, mendefinisikan administrasi kontrak sebagai “upaya pengelolaan atas kontrak dalam periode pelaksanaannya sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut.”
Tujuan pokok dari administrasi kontrak, sebagaimana diuraikan dalam Modul 1, adalah untuk “mendapatkan barang-barang (hasil pekerjaan konstruksi) yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kontrak secara ekonomis, efisien dan efektif”.3 Lebih lanjut, administrasi kontrak juga bertujuan untuk mendorong “peningkatan kinerja berkelanjutan selama masa berlakunya kontrak”.3 Administrasi kontrak yang baik akan menjamin bahwa pengguna akhir (Pengguna Jasa) merasa puas dengan hasil pekerjaan yang diterima. Prosedur administrasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik memastikan bahwa semua pihak yang terikat dalam kontrak memahami dengan pasti siapa yang bertanggung jawab melakukan apa, kapan suatu tindakan harus dilakukan, dan bagaimana prosedur pelaksanaannya.3
Pentingnya administrasi kontrak tidak boleh diabaikan. Administrasi kontrak yang efektif berfungsi sebagai mekanisme vital untuk mencegah timbulnya sengketa, bukan semata-mata sebagai alat untuk menangani masalah setelah masalah tersebut muncul dan berkembang. Dengan adanya dokumentasi yang rapi, komunikasi yang transparan, dan pemahaman yang sama mengenai isi kontrak, berbagai potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan sejak dini. Sebagaimana ditekankan dalam Modul 1, administrasi kontrak melibatkan “penciptaan hubungan kerja yang baik antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Kontraktor yang penting untuk mengantisipasi dan mengelola resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya di masa mendatang”.3 Jurnal penelitian juga menggarisbawahi peran krusial administrasi kontrak dalam mengelola risiko hukum dan secara signifikan mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.22 Dengan demikian, investasi dalam sistem administrasi kontrak yang solid dan didukung oleh personil yang kompeten merupakan langkah preventif yang cerdas, yang pada akhirnya dapat menghindarkan para pihak dari biaya penyelesaian sengketa yang jauh lebih besar dan proses yang berlarut-larut.
4.2. Perspektif Administrasi Proyek: Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan Enjinir
Setiap pihak utama yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki perspektif dan kepentingan yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan administrasi proyek, meskipun tujuan akhirnya adalah keberhasilan proyek secara keseluruhan. Pemahaman terhadap perspektif masing-masing pihak ini menjadi kunci untuk membangun kolaborasi yang efektif dan sinergis.
- Bagi Pengguna Jasa: Dari sudut pandang Pengguna Jasa, administrasi proyek bertujuan utama untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik berupa bangunan maupun kelengkapannya, benar-benar sesuai dengan spesifikasi, kualitas, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.3 Pengguna Jasa berkepentingan agar kontrak dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan investasi proyek tercapai secara optimal. Administrasi kontrak bagi Pengguna Jasa juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memantau kinerja Penyedia Jasa dan memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan kontraktual.
- Bagi Penyedia Jasa/Kontraktor: Bagi Penyedia Jasa atau Kontraktor, administrasi proyek difokuskan pada pengelolaan kontrak selama masa pelaksanaan agar target-target internal perusahaan tercapai, yaitu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan aspek biaya yang telah dianggarkan, mutu yang dipersyaratkan, dan waktu yang telah dijadwalkan.3 Selain itu, administrasi kontrak yang baik membantu Penyedia Jasa dalam mengelola risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba yang wajar, membangun citra perusahaan yang baik melalui kinerja profesional, serta memastikan semua hak kontraktualnya terpenuhi, termasuk hak atas pembayaran.18
- Bagi Enjinir (Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi): Enjinir, dalam kapasitasnya sebagai wakil atau penasihat ahli Pengguna Jasa, memiliki perspektif administrasi proyek yang berorientasi pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan/atau manajemen konstruksi secara efektif.3 Administrasi proyek bagi Enjinir bertujuan untuk memastikan bahwa Kontraktor Pelaksana mematuhi seluruh ketentuan kontrak, termasuk spesifikasi teknis, gambar rencana, dan standar kualitas. Enjinir juga bertanggung jawab untuk memberikan saran teknis yang akurat kepada Pengguna Jasa, melakukan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan, memverifikasi klaim pembayaran, dan mengelola dokumentasi proyek atas nama Pengguna Jasa.
Meskipun terdapat perbedaan fokus dalam tujuan administrasi proyek bagi masing-masing pihak, penting untuk disadari bahwa ketiga pihak utama ini (Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan Enjinir) memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi satu sama lain dalam hal pertukaran informasi dan pelaksanaan tindakan-tindakan administratif. Sebagai contoh, Kontraktor sangat bergantung pada persetujuan teknis dan rekomendasi pembayaran yang tepat waktu dari Enjinir, yang kemudian menjadi dasar bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pembayaran. Sebaliknya, Pengguna Jasa dan Enjinir membutuhkan laporan kemajuan pekerjaan yang akurat dan data kualitas yang valid dari Kontraktor untuk dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kegagalan satu pihak dalam menjalankan fungsi administrasi kontraknya secara baik dan benar dapat secara langsung berdampak negatif pada kinerja dan kepentingan pihak-pihak lainnya. Jika Kontraktor, misalnya, gagal menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan secara memadai, sebagaimana menjadi salah satu Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK 3) 3, maka Enjinir akan kesulitan melakukan verifikasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan Pengguna Jasa menunda proses pembayaran. Oleh karena itu, implementasi sistem administrasi kontrak yang terintegrasi, atau setidaknya terkoordinasi dengan baik antar semua pihak, yang didukung oleh alur komunikasi yang jelas dan penggunaan format dokumentasi standar, menjadi sangat krusial untuk kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi.
4.3. Prinsip-Prinsip Dasar dan Tahapan Administrasi Kontrak yang Efektif
Administrasi kontrak yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip penerapan yang baik (best practice principles).3 Beberapa prinsip fundamental yang relevan meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini, misalnya, harus tercermin dalam proses pemberian insentif sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 78.13
Administrasi kontrak pada dasarnya mengikuti siklus hidup proyek, yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Modul 1 menyajikan diagram “Tahapan Pelaksanaan Kontrak” yang menggambarkan alur proses mulai dari tahap pengadaan hingga penyelesaian akhir proyek, yaitu: Penerbitan Dokumen Lelang → Penyampaian Dokumen Penawaran → Penerbitan Surat Penunjukan → Tanggal Mulainya Pekerjaan → Masa Pelaksanaan Pekerjaan → Penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1/PHO) → Masa Pemberitahuan Cacat Mutu (Masa Pemeliharaan) → Penerbitan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2/FHO) → Pengembalian Jaminan Pelaksanaan (Akhir Kontrak).3
Selain tahapan pelaksanaan kontrak secara umum, terdapat juga tahapan spesifik dalam konteks pengendalian kontrak, khususnya dalam kerangka pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden terkait pengadaan, tahapan pengendalian kontrak meliputi: monitoring pelaksanaan sesuai dengan rencana pengendalian, identifikasi terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, dan tindakan perbaikan atas penyimpangan atau perubahan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi.23
Dari perspektif pembentukan kontrak itu sendiri, terdapat beberapa langkah atau tahapan penyusunan kontrak yang krusial, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai literatur 24, yaitu:
- Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
- Definisi yang jelas dan terperinci mengenai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Penentuan jadwal pelaksanaan dan durasi proyek yang realistis.
- Pengaturan mengenai biaya proyek dan mekanisme pembayaran.
- Pembagian dan alokasi risiko antara para pihak.
- Pemenuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku.
- Penetapan mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan ganti rugi.
- Penandatanganan kontrak oleh para pihak yang berwenang.
Penting untuk dicermati bahwa diagram “Tahapan Pelaksanaan Kontrak” yang terdapat dalam Modul 1 3 lebih cenderung menggambarkan alur proses secara makro, mulai dari proses pengadaan hingga penyelesaian akhir proyek. Sementara itu, administrasi kontrak yang efektif, sebagaimana menjadi fokus dalam CPMK 1 3 dan diuraikan lebih lanjut dalam materi perkuliahan 3, mencakup serangkaian aktivitas manajerial dan dokumentasi yang jauh lebih detail yang terjadi di dalam setiap tahapan tersebut. Administrasi kontrak bukanlah sekadar daftar urutan kejadian, melainkan sebuah proses pengelolaan yang aktif dan berkelanjutan terhadap hak, kewajiban, risiko, perubahan, pembayaran, dan seluruh dokumentasi terkait selama “Masa Pelaksanaan Pekerjaan” dan tahapan-tahapan krusial lainnya. Ini menggarisbawahi bahwa administrasi kontrak adalah sebuah proses yang dinamis, yang memerlukan pemantauan berkelanjutan, pelaporan yang akurat, manajemen perubahan yang responsif, dan komunikasi yang konstan serta efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.
BAB V: TERMINOLOGI FUNDAMENTAL DALAM KONTRAK KONSTRUKSI
Pemahaman yang akurat terhadap terminologi kunci yang sering digunakan dalam kontrak konstruksi merupakan dasar penting bagi para profesional di bidang ini. Kesalahan interpretasi terhadap istilah-istilah tertentu dapat berakibat pada kesalahpahaman, perselisihan, bahkan sengketa hukum. Bab ini akan membahas beberapa terminologi fundamental yang relevan.
5.1. Persyaratan Kontrak (Conditions of Contract)
Istilah “persyaratan kontrak” atau conditions of contract merujuk pada klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen kontrak yang secara spesifik mendefinisikan hak, kewajiban, prosedur pelaksanaan, alokasi risiko, dan berbagai aspek lain yang mengatur hubungan antara para pihak. Menurut Garner (2004), “persyaratan” (conditions) adalah “suatu kejadian mendatang dan tidak pasti di mana keberadaan atau batas suatu kewajiban atau tanggung jawab tergantung padanya; atau suatu tindakan atau kejadian yang tidak pasti yang menambah atau meniadakan suatu kewajiban untuk menghasilkan kinerja yang dijanjikan”.3 Definisi ini menyoroti sifat kondisional dari beberapa kewajiban dalam kontrak.
Tay and Tang (2004) memberikan perspektif lain, menyatakan bahwa “persyaratan” (a condition) adalah “bagian pokok dari suatu kontrak yang mengarah pada akar kontrak (root of the contract). Pelanggaran terhadap suatu persyaratan memberikan hak kepada pihak yang dicederai untuk tidak mengakui kontrak (menolak pelaksanaan lebih lanjut) dan mengajukan klaim ganti rugi”.3 Pandangan ini menekankan pada signifikansi atau materialitas dari suatu persyaratan.
Dalam praktik kontrak konstruksi, persyaratan kontrak dapat ditemukan dalam berbagai bagian dokumen kontrak, seperti Syarat-Syarat Umum Kontrak (General Conditions of Contract – GCC) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Special Conditions of Contract – SCC). Pelanggaran terhadap persyaratan yang bersifat material atau fundamental dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran.
Penting untuk dicermati adanya perbedaan antara “conditions” (persyaratan pokok atau fundamental) dan “warranties” (persyaratan tambahan atau jaminan) dalam teori hukum kontrak umum, khususnya dalam tradisi common law yang sering mempengaruhi standar kontrak internasional. Meskipun KUHPerdata Indonesia tidak secara eksplisit membuat pembedaan ini dengan terminologi yang sama, konsep materialitas pelanggaran tetap relevan. Pelanggaran terhadap suatu condition (persyaratan yang dianggap sebagai inti dari kontrak) dapat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri kontrak dan menuntut ganti rugi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap suatu warranty (persyaratan yang dianggap kurang fundamental) umumnya hanya memberikan hak untuk menuntut ganti rugi, tanpa hak untuk mengakhiri kontrak. Definisi dari Tay and Tang 3 yang menyebutkan “istilah vital… yang mengarah pada akar kontrak” dan bahwa pelanggarannya “memberikan hak untuk menolak kontrak” mencerminkan karakteristik dari condition ini. Pemahaman ini menjadi relevan karena banyak kontrak konstruksi berskala besar di Indonesia, terutama yang melibatkan pihak asing atau pendanaan internasional, seringkali mengadopsi atau merujuk pada standar kontrak internasional seperti FIDIC, yang secara eksplisit disebutkan sebagai bahan pendukung dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini.3 Oleh karena itu, identifikasi secara cermat mengenai mana saja persyaratan yang bersifat fundamental dalam suatu kontrak konstruksi menjadi sangat penting, karena pelanggaran terhadapnya dapat membuka opsi bagi pihak yang tidak bersalah untuk mengambil langkah hukum yang lebih drastis, termasuk pengakhiran kontrak.
5.2. Strategi dalam Konteks Kontrak
Istilah “strategi” dalam konteks umum merujuk pada suatu rencana atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Salim mendefinisikannya sebagai “proses dalam perencanaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan sasaran jangka panjang”.3 Allen menyatakan bahwa strategi adalah “rencana atau cara untuk mencapai suatu kebutuhan” 3, sementara Ali et al. menggambarkannya sebagai “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.3
Dalam konteks kontrak konstruksi, “strategi” dapat merujuk pada pendekatan atau rencana yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing pihak (Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, maupun Enjinir) untuk mencapai tujuan kontraktual mereka, mengelola risiko yang teridentifikasi, dan menangani potensi masalah atau perselisihan yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, dapat berupa strategi negosiasi dalam penyusunan kontrak awal, strategi pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efisiensi biaya dan waktu, strategi manajemen klaim jika terjadi peristiwa yang berpotensi menimbulkan klaim, atau strategi penyelesaian sengketa jika perselisihan tidak dapat dihindari. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini juga menyebutkan “Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Conditions of Contract” sebagai salah satu materi pendukung, yang menunjukkan relevansi konsep strategi dalam pengelolaan aspek kontraktual.3
Sebuah strategi administrasi kontrak yang bersifat proaktif, yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban formal tetapi juga pada upaya pencegahan masalah, pemeliharaan hubungan kerja yang baik antar para pihak, dan antisipasi risiko, cenderung akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan strategi yang hanya bersifat reaktif terhadap klaim dan sengketa yang sudah terlanjur muncul. Definisi strategi yang menekankan pada aspek “perencanaan,” “kebijaksanaan,” “sasaran jangka panjang,” dan “rencana cermat” 3, sejalan dengan tujuan administrasi kontrak yang antara lain adalah “menciptakan hubungan kerja yang baik” dan “mengantisipasi risiko”.3 Dengan demikian, penggabungan kedua konsep ini menyiratkan bahwa strategi administrasi kontrak yang ideal adalah strategi yang terencana dengan matang untuk memelihara kolaborasi yang konstruktif dan secara proaktif mengidentifikasi serta memitigasi potensi risiko, bukan sekadar menunggu masalah timbul baru kemudian mencari solusi. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi sebaiknya mengembangkan strategi kontrak mereka sejak tahap awal, yang mencakup bagaimana mereka akan berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menangani setiap perubahan atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek.
5.3. Klaim Konstruksi (Construction Claims)
Klaim merupakan suatu hal yang sangat lazim terjadi dalam industri konstruksi.11 Kompleksitas proyek, durasi yang panjang, ketidakpastian kondisi lapangan, dan keterlibatan banyak pihak seringkali memicu timbulnya situasi di mana salah satu pihak merasa berhak atas suatu kompensasi atau penyesuaian kontrak.
Secara definitif, Garner mengartikan klaim sebagai “suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu pemulihan hukum yang berhak diperoleh seseorang”.3 Hardjomuljadi et al. memberikan perspektif bahwa klaim adalah “suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu di mana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya karena yang bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali”.3 Martin and Law mendefinisikannya sebagai “suatu tuntutan atas suatu ganti rugi atau memastikan suatu hak, terutama hak untuk membawa kasus tertentu ke pengadilan”.3 Dalam konteks regulasi yang lebih lama (PP No. 24 Tahun 2005), klaim diartikan sebagai “jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja (pengguna jasa) sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak”.3
Klaim dalam proyek konstruksi dapat diajukan baik oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) terhadap Pengguna Jasa, maupun sebaliknya. Penyebab timbulnya klaim sangat beragam, di antaranya adalah perubahan desain atau lingkup pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, keterlambatan yang disebabkan oleh pihak lain, perbedaan kondisi lapangan yang signifikan dari yang diasumsikan, informasi tender yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan lain sebagainya.11 Bentuk klaim yang paling umum diajukan adalah permintaan tambahan biaya dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.11
Manajemen klaim yang baik melibatkan serangkaian prosedur yang jelas, mulai dari identifikasi peristiwa penyebab klaim, pemberitahuan (notifikasi) secara tepat waktu kepada pihak lain, pengumpulan dan penyajian dokumentasi pendukung yang kuat, hingga proses evaluasi, negosiasi, dan penyelesaian klaim tersebut.11
Salah satu aspek paling krusial dalam proses pengajuan klaim adalah pemenuhan terhadap persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam kontrak, khususnya terkait pemberitahuan klaim. Banyak kontrak standar, termasuk FIDIC, menetapkan batas waktu yang ketat bagi pihak yang akan mengajukan klaim untuk memberitahukan niatnya kepada pihak lain setelah menyadari atau seharusnya menyadari adanya peristiwa atau keadaan yang menimbulkan klaim tersebut.11 Kegagalan dalam mematuhi prosedur pemberitahuan ini, misalnya terlambat menyampaikan notifikasi, dapat berakibat fatal bagi keberhasilan klaim, bahkan jika klaim tersebut secara substantif memiliki dasar yang kuat. Pihak yang mengajukan klaim dapat kehilangan haknya atas perpanjangan waktu atau pembayaran tambahan, dan pihak lain dapat dibebaskan dari semua kewajiban terkait klaim tersebut.11 Ini seringkali merupakan condition precedent, yaitu suatu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum substansi klaim dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, para pihak harus sangat disiplin dalam mematuhi seluruh persyaratan prosedural terkait klaim yang diatur dalam kontrak. Pelatihan mengenai manajemen klaim, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap aspek prosedural dan substantif, menjadi sangat penting bagi para praktisi konstruksi.
Perlu juga diwaspadai adanya “tendensi tidak sehat untuk memperbesar klaim oleh kontraktor,” sebagaimana dikutip oleh Kumaraswamy 3, atau “klaim kontraktor yang berlebihan” yang disebut sebagai salah satu penyebab sengketa dari perspektif pengguna jasa.19 Hal ini mengindikasikan bahwa pengajuan klaim tidak selalu murni didasarkan pada hak kontraktual yang sah, tetapi terkadang dapat dipengaruhi oleh strategi komersial untuk menutupi harga penawaran yang terlalu rendah atau bahkan didasari oleh itikad yang kurang baik. Fenomena ini dapat memperburuk hubungan antar para pihak dan mempersulit proses penyelesaian klaim secara adil dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya klaim yang didasarkan pada fakta yang akurat, analisis yang jujur dan objektif, serta niat baik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara adil, bukan menjadikan klaim sebagai alat untuk mencari keuntungan yang tidak semestinya atau sebagai ajang perseteruan.
5.4. Sengketa Konstruksi (Construction Disputes)
Sengketa konstruksi dapat diartikan sebagai eskalasi dari klaim atau ketidaksepakatan antara para pihak dalam kontrak konstruksi yang tidak berhasil diselesaikan melalui negosiasi atau mekanisme penyelesaian informal lainnya. Chow Kok Fong (2006) mendefinisikan sengketa sebagai “perbedaan posisi atas suatu masalah yang dimintakan penetapannya kepada suatu pengadilan atau majelis”.3 Kumaraswamy (1997), mengutip Collins (1995), menyatakan bahwa sengketa berasal dari konflik, yaitu “ketidak sepakatan dan perbedaan pendapat mengenai sesuatu yang penting”.3 Sengketa seringkali timbul akibat adanya perbedaan persepsi yang tajam mengenai legitimasi atau besaran jumlah suatu klaim yang diajukan.3
Penyebab umum terjadinya sengketa konstruksi sangat beragam dan seringkali bersifat multifaktorial. Beberapa penyebab yang sering diidentifikasi meliputi perbedaan interpretasi terhadap klausul-klausul kontrak, perubahan lingkup pekerjaan yang signifikan, keterlambatan pelaksanaan proyek (baik yang disebabkan oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa), masalah terkait pembayaran, perselisihan mengenai kualitas pekerjaan, serta kondisi lapangan yang tidak terduga atau berbeda secara signifikan dari yang diinformasikan dalam dokumen tender.19
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UUJK No. 2 Tahun 2017 Pasal 88 menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari musyawarah untuk mufakat, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi).8 Pemilihan mekanisme ini idealnya telah disepakati dan dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.15
Salah satu akar penyebab utama timbulnya sengketa konstruksi adalah adanya ketidakjelasan atau ambiguitas dalam dokumen kontrak itu sendiri. Semakin jelas, komprehensif, dan tidak ambigu suatu kontrak dirumuskan, semakin kecil potensi terjadinya perbedaan interpretasi yang dapat berujung pada sengketa. Berbagai sumber mengidentifikasi “ambiguitas bahasa hukum dan klausul yang tidak mencakup perubahan lapangan” 22 atau “klausa dalam kontrak yang ambigu” 19 sebagai pemicu sengketa. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya investasi waktu, keahlian, dan kecermatan dalam tahap penyusunan dan perancangan draf kontrak. Keterlibatan ahli hukum konstruksi yang berpengalaman dalam proses penyusunan dan review kontrak sangat dianjurkan untuk meminimalkan potensi ambiguitas dan memastikan bahwa berbagai skenario potensial telah diantisipasi dan diatur secara memadai dalam kontrak.
Pilihan forum atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam kontrak juga memiliki implikasi strategis yang signifikan terhadap bagaimana suatu sengketa akan ditangani di kemudian hari. UUJK No. 2/2017 dan UU No. 30/1999 memberikan beragam opsi. Arbitrase, misalnya, seringkali dianggap memiliki beberapa keunggulan seperti proses yang relatif lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan umum, sifat kerahasiaan proses dan putusan, serta penanganan sengketa oleh arbiter yang memiliki keahlian spesifik di bidang konstruksi. Namun, biaya awal untuk arbitrase terkadang bisa lebih tinggi. Sebaliknya, penyelesaian melalui pengadilan mungkin memakan waktu lebih lama karena adanya mekanisme banding dan kasasi, tetapi biaya awalnya bisa jadi lebih rendah. Para pihak harus mempertimbangkan dengan matang berbagai faktor ini, termasuk jenis sengketa yang mungkin timbul, kompleksitas masalah, kebutuhan akan kerahasiaan, serta pertimbangan biaya dan waktu, ketika melakukan negosiasi dan menyepakati klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak mereka.
Berikut adalah tabel yang merangkum perbandingan definisi istilah-istilah kunci dalam kontrak konstruksi:
Tabel 5.1: Perbandingan Definisi Istilah Kunci dalam Kontrak Konstruksi
| Istilah | Sumber Definisi (Ahli/Regulasi) | Definisi Inti | Implikasi Praktis |
| Persyaratan Kontrak | Garner (2004), Tay & Tang (2004) | Kejadian/tindakan yang memicu/meniadakan kewajiban; bagian pokok kontrak yang pelanggarannya berakibat serius. | Menentukan hak & kewajiban; pelanggaran persyaratan material dapat menyebabkan pemutusan kontrak dan klaim ganti rugi. |
| Strategi | Salim, Allen, Ali et al. | Proses perencanaan, rencana, atau cara cermat untuk mencapai sasaran/kebutuhan jangka panjang. | Pendekatan para pihak untuk mencapai tujuan kontrak, mengelola risiko, dan menangani masalah (misalnya, strategi klaim, negosiasi). |
| Klaim Konstruksi | Garner, Hardjomuljadi, PP 24/2005 | Tuntutan atas uang/pemulihan hukum/penggantian biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak awal. | Umum terjadi akibat perubahan, keterlambatan, dll.; memerlukan manajemen klaim yang baik (prosedur, dokumentasi, negosiasi). |
| Sengketa Konstruksi | Chow, Kumaraswamy | Perbedaan posisi atas masalah yang dimintakan penetapan; eskalasi dari klaim/ketidaksepakatan tak terselesaikan. | Memerlukan mekanisme penyelesaian (musyawarah, mediasi, arbitrase, litigasi); pencegahan melalui kontrak yang jelas lebih diutamakan. |
Tabel ini bertujuan untuk membantu dalam memahami terminologi esensial yang akan sering ditemui dalam studi maupun praktik di bidang hukum dan administrasi kontrak konstruksi. Dengan menyandingkan definisi dari berbagai sumber dan menyoroti implikasi praktisnya, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana istilah-istilah ini beroperasi dalam dinamika proyek konstruksi, sejalan dengan pembahasan dalam Modul 1.3
BAB VI: DOKUMENTASI DAN PROSEDUR KUNCI DALAM SIKLUS HIDUP KONTRAK KONSTRUKSI
Administrasi kontrak yang efektif sangat bergantung pada kelengkapan, keakuratan, dan ketertiban dokumentasi serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Setiap tahapan dalam siklus hidup kontrak konstruksi, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian, memiliki serangkaian dokumen dan prosedur kunci yang harus dikelola dengan cermat.
6.1. Komponen Minimal Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi (PP No. 22 Tahun 2020)
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Kontrak Kerja Konstruksi bukanlah satu dokumen tunggal, melainkan suatu kesatuan dari berbagai dokumen yang saling melengkapi. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Pasal 76 secara spesifik merinci komponen-komponen minimum yang harus termuat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi.13 Kelengkapan dokumen ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, mengurangi ambiguitas, dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pihak. Dokumen-dokumen minimum tersebut adalah:
- Surat Perjanjian (Agreement Letter): Merupakan dokumen induk yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Surat Perjanjian ini setidaknya memuat identitas para pihak, konsiderasi (latar belakang dan tujuan kontrak), rumusan atau lingkup pekerjaan secara garis besar, pokok-pokok kesepakatan penting seperti harga kontrak dan jangka waktu pelaksanaan, serta daftar dokumen-dokumen lain yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak beserta urutan keberlakuan atau hierarkinya jika terjadi pertentangan antar dokumen.
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Special Conditions of Contract – SCC): Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik untuk proyek tertentu. SCC mengakomodasi informasi detail mengenai pekerjaan, penyesuaian terhadap Syarat-Syarat Umum Kontrak, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan karakteristik unik proyek tersebut.
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (General Conditions of Contract – GCC): Memuat ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk sebagian besar kontrak konstruksi, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, prosedur administrasi, alokasi risiko, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, dan lain-lain, yang didasarkan pada sistem penyampaian pekerjaan, lingkup pekerjaan, metode pembayaran, dan sistem perhitungan hasil pekerjaan yang dipilih.
- Dokumen Pengguna Jasa: Ini adalah dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Pengguna Jasa dan menjadi bagian dari dokumen pemilihan (dokumen lelang/tender). Dokumen ini menjadi dasar bagi Penyedia Jasa dalam menyusun proposal atau penawarannya, dan umumnya mencakup spesifikasi teknis pekerjaan, gambar-gambar rencana (desain), serta daftar kuantitas dan harga (jika menggunakan sistem harga satuan) atau rincian keluaran (jika menggunakan sistem lump sum).
- Proposal atau Penawaran Penyedia Jasa: Dokumen yang diajukan oleh Penyedia Jasa sebagai tanggapan atas dokumen pemilihan dari Pengguna Jasa. Proposal ini biasanya berisi metode pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan, harga penawaran, jadwal pelaksanaan, dan rincian sumber daya yang akan digunakan.
- Berita Acara Rapat: Mencakup catatan resmi mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa selama proses evaluasi proposal atau penawaran, termasuk klarifikasi atas hal-hal yang mungkin menimbulkan keraguan.
- Surat Pernyataan dari Pengguna Jasa: Dokumen yang menyatakan penerimaan atau persetujuan Pengguna Jasa terhadap proposal atau penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa.
- Surat Pernyataan dari Penyedia Jasa: Dokumen yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Selain PP No. 22/2020, UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 47 juga telah menggariskan muatan minimal yang harus ada dalam Kontrak Kerja Konstruksi, yang sebagian besar substansinya tercermin dan dirinci lebih lanjut dalam ketentuan PP No. 22/2020 tersebut.8 Bahkan, regulasi yang lebih lama seperti yang dirujuk dalam 29 (mengacu pada UU No. 18 Tahun 1999) juga telah menyebutkan komponen-komponen wajib serupa, seperti identitas para pihak, uraian pekerjaan, jangka waktu, nilai kontrak dan cara pembayaran, hak dan kewajiban, syarat teknis, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kebutuhan akan elemen-elemen dasar tersebut untuk membentuk suatu kontrak konstruksi yang komprehensif.
Meskipun PP No. 22/2020 telah menetapkan standar “dokumen minimum”, praktik terbaik dalam industri konstruksi seringkali menyertakan dokumen-dokumen tambahan sebagai bagian integral dari kontrak untuk meningkatkan kejelasan dan kemudahan pengelolaan. Contohnya adalah Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) atau dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), jadwal pelaksanaan pekerjaan yang lebih detail (misalnya menggunakan Kurva S atau diagram jaringan), dan dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan. Sebagai contoh, standar format administrasi proyek yang dirujuk dalam 30 mencantumkan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebagai bagian dari dokumen yang dibahas dan disiapkan sejak Rapat Pra-Konstruksi (PCM), yang merupakan tahap sangat awal dalam pelaksanaan. Ini mengindikasikan bahwa dokumen-dokumen tersebut, meskipun mungkin tidak secara eksplisit tercantum sebagai dokumen kontrak minimum dalam Pasal 76 PP No. 22/2020, dianggap esensial dalam praktik administrasi proyek konstruksi modern. Oleh karena itu, para pihak sebaiknya tidak hanya terpaku pada daftar minimum yang ditetapkan oleh peraturan, tetapi juga mempertimbangkan untuk memasukkan dan mengintegrasikan dokumen-dokumen lain yang relevan dan penting demi tercapainya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan pengelolaan proyek yang baik ke dalam satu set dokumen kontrak yang utuh.
Satu aspek krusial yang harus diperhatikan adalah penentuan “hierarki dokumen” atau urutan keberlakuan dokumen dalam kontrak. Pasal 76 PP No. 22/2020 13 menyebutkan bahwa Surat Perjanjian harus memuat “daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarkinya”. Klausul hierarki ini sangat penting karena jika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara isi satu dokumen dengan dokumen lainnya (misalnya, antara spesifikasi teknis dengan gambar rencana), maka hierarki yang telah disepakati akan menentukan dokumen mana yang memiliki keberlakuan lebih tinggi dan harus diikuti. Tanpa adanya hierarki yang jelas, perbedaan antar berbagai dokumen kontrak dapat menimbulkan kebingungan, perselisihan interpretasi, dan pada akhirnya dapat memicu sengketa mengenai standar atau lingkup pekerjaan yang sebenarnya harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penyusunan klausul hierarki dokumen harus dilakukan dengan sangat cermat dan disepakati bersama oleh para pihak untuk menghindari masalah interpretasi di kemudian hari.
6.2. Administrasi Selama Pelaksanaan: Dari PCM, MC0, hingga Laporan Rutin
Setelah kontrak ditandatangani, dimulailah tahap pelaksanaan proyek yang sarat dengan berbagai aktivitas administratif. Setiap tahapan dalam pelaksanaan proyek konstruksi memerlukan dokumentasi administrasi yang spesifik dan terstandarisasi untuk memastikan kelancaran, pengendalian, dan akuntabilitas.
- Rapat Pra-Konstruksi (Pre-Construction Meeting – PCM): Ini adalah rapat awal yang sangat penting, diadakan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Kontraktor), Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai seluruh aspek Dokumen Kontrak dan rencana pelaksanaan pekerjaan.30 Dokumen-dokumen yang terkait dengan PCM meliputi Surat Undangan Rapat, Risalah Rapat PCM yang mencatat semua pembahasan dan kesepakatan, dokumentasi pelaksanaan rapat (misalnya foto), Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) atau Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), serta Rencana Mutu Kontrak (RMK).30 Materi pembahasan dalam PCM biasanya mencakup RKK, organisasi kerja di lapangan, metode pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan, dan jadwal pelaksanaan detail.30
- Pemeriksaan Bersama Lapangan Awal (Mutual Check 0 – MC0): MC0 adalah proses pengukuran dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Jasa (atau wakilnya) dan Penyedia Jasa di awal masa pelaksanaan proyek.30 Tujuannya adalah untuk memverifikasi kondisi aktual lapangan, mencocokkannya dengan data dan gambar perencanaan, serta mengidentifikasi potensi perbedaan atau perubahan yang mungkin diperlukan. Dokumen-dokumen yang terkait dengan MC0 meliputi Surat Perintah Pengukuran, Undangan Pengukuran Bersama, Berita Acara Pengukuran Lapangan Bersama, Rincian Indikasi Perubahan yang teridentifikasi (jika ada), pembaruan terhadap Master Schedule berdasarkan hasil MC0, Gambar Hasil Pengukuran Lapangan, dan Laporan komprehensif mengenai hasil pengukuran bersama dan pembahasannya.30 Hasil MC0 ini dapat menjadi dasar untuk penyesuaian volume pekerjaan atau bahkan perubahan desain minor jika diperlukan.
- Instruksi Harian (Daily Instruction): Selama pelaksanaan, seringkali diperlukan instruksi atau arahan teknis dari Konsultan Pengawas kepada Kontraktor. Instruksi harian ini idealnya dicatat secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari.30
- Izin Kerja/Izin Pelaksanaan Pekerjaan (Work Permit): Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memiliki risiko tinggi atau memerlukan koordinasi khusus, seringkali diperlukan izin kerja formal sebelum pekerjaan tersebut dapat dimulai. Dokumen ini memastikan bahwa semua aspek keselamatan dan prosedur telah dipertimbangkan.30
- Pengajuan Material dan Persetujuan (Material Approval Request): Kontraktor wajib mengajukan material yang akan digunakan dalam proyek kepada Konsultan Pengawas atau Pengguna Jasa untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan pengajuan spesifikasi material, contoh material, dan hasil uji (jika diperlukan) untuk memastikan kesesuaian dengan standar kontrak.30
- Laporan Kemajuan (Progress Report): Kontraktor berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala (misalnya mingguan atau bulanan) kepada Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas. Laporan ini biasanya berisi informasi mengenai prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai, perbandingan antara progres aktual dengan jadwal rencana, kendala yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut.30 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini juga secara khusus menyebutkan “Kasus Administrasi Pelaporan (Progress Report and Monitoring)” sebagai salah satu materi pembelajaran 3, yang menunjukkan pentingnya aspek ini.
Selain dokumen-dokumen spesifik di atas, terdapat berbagai dokumen administrasi proyek lainnya yang juga penting untuk dikelola, seperti proposal proyek awal, rencana pelaksanaan proyek yang detail, jadwal waktu (time schedule) yang terus diperbarui, daftar identifikasi dan mitigasi risiko proyek, serta dokumen-dokumen penutup proyek di akhir pelaksanaan.30
Kelengkapan dan ketertiban seluruh dokumentasi administrasi selama masa pelaksanaan proyek bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan memiliki peran yang sangat strategis. Dokumentasi yang baik dan akurat berfungsi sebagai alat bukti utama jika terjadi perselisihan interpretasi kontrak, klaim atas tambahan biaya atau waktu, atau bahkan sengketa hukum. Sebagaimana ditekankan dalam berbagai sumber, “pentingnya dokumentasi dalam administrasi kontrak” tidak dapat diremehkan.22 Jika terjadi klaim keterlambatan, misalnya, catatan harian proyek, laporan kemajuan mingguan/bulanan, dan risalah rapat koordinasi dapat menjadi bukti krusial untuk menunjukkan pihak mana yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Demikian pula, jika ada klaim terkait perubahan pekerjaan, maka instruksi tertulis dari pihak yang berwenang dan persetujuan formal atas perubahan tersebut menjadi bukti yang sangat diperlukan.11 Kurangnya dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan salah satu penyebab utama kegagalan suatu klaim untuk dapat diterima.26 Oleh karena itu, setiap entitas yang terlibat dalam proyek konstruksi harus memiliki sistem yang mapan dan terstruktur untuk pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan seluruh dokumen proyek. Pelatihan bagi seluruh staf proyek mengenai pentingnya dan tata cara dokumentasi yang benar dan konsisten menjadi sangat esensial.
Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi untuk administrasi dan dokumentasi proyek semakin meluas. Digitalisasi proses administrasi kontrak, seperti yang disinggung dalam 22, dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek atau Enterprise Resource Planning (ERP) khusus konstruksi memungkinkan pengelolaan dokumen secara digital, pemantauan progres proyek secara real-time, dan fasilitasi alur kerja persetujuan yang lebih cepat dan terdokumentasi. Hal ini menunjukkan adanya tren pergeseran dari administrasi manual yang seringkali rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan kesulitan akses data, menuju sistem yang lebih terotomatisasi dan terintegrasi. Perusahaan konstruksi yang ingin meningkatkan daya saing dan efektivitas operasionalnya perlu mempertimbangkan secara serius investasi dalam teknologi manajemen proyek dan administrasi kontrak.
6.3. Manajemen Perubahan Kontrak: Contract Change Order (CCO) / Variation Order (VO)
Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam banyak proyek konstruksi. Kompleksitas desain, kondisi lapangan yang tidak terduga, perubahan kebutuhan Pengguna Jasa, atau bahkan inovasi teknis selama pelaksanaan dapat memicu perlunya modifikasi terhadap lingkup, jadwal, biaya, atau kualitas pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak awal. Manajemen perubahan kontrak yang efektif, yang sering diwujudkan melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) atau Variation Order (VO), menjadi sangat penting untuk mengendalikan dampak perubahan tersebut dan menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai koridor yang diharapkan.
Secara definitif, CCO atau VO adalah suatu modifikasi atau perubahan formal terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak awal setelah kontrak tersebut ditandatangani.3 Perubahan ini dapat berupa penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis, perubahan desain, penambahan atau penghapusan item pekerjaan, atau penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan dan biaya kontrak.
Dalam konteks proyek pemerintah di Indonesia, dasar hukum untuk pelaksanaan CCO, meskipun telah ada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seringkali masih merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, khususnya Pasal 87, untuk aspek perubahan kontrak.35 Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses CCO pada proyek pemerintah umumnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Kontraktor).35
Penyebab umum diterbitkannya CCO antara lain adalah adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi aktual lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Kontrak, adanya perubahan desain yang diminta oleh Pengguna Jasa, atau timbulnya kebutuhan akan pekerjaan tambah atau kurang yang tidak terantisipasi sebelumnya.35
Meskipun prosedur detail pelaksanaan CCO tidak dirinci secara eksplisit dalam 37, secara umum proses CCO melibatkan beberapa tahapan, antara lain: identifikasi kebutuhan akan perubahan, pengajuan usulan perubahan (biasanya oleh Kontraktor jika ada temuan lapangan atau oleh Pengguna Jasa jika ada perubahan kebutuhan), evaluasi teknis dan biaya terhadap usulan perubahan, proses negosiasi antara para pihak, persetujuan formal atas perubahan, penerbitan dokumen CCO atau VO, dan yang paling penting, formalisasi perubahan tersebut melalui suatu adendum atau amandemen terhadap kontrak awal.11
Dokumentasi yang terkait dengan proses CCO sangatlah penting dan harus dikelola dengan cermat. Standar format administrasi proyek 30 menyebutkan berbagai dokumen yang relevan dengan CCO (yang sering disebut juga sebagai Addendum Kontrak), di antaranya adalah Surat Perjanjian Kontrak Addendum, pembaruan terhadap Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Addendum, Surat Keputusan mengenai Pekerjaan Tambah Kurang, Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi terkait perubahan, Laporan Progres Pekerjaan yang merekomendasikan addendum, Penawaran Harga untuk Addendum Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Addendum, serta pembaruan terhadap Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Addendum.30 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini juga mengalokasikan waktu khusus untuk membahas “Kasus Administrasi Perintah Perubahan (Variation Order)” 3, yang menandakan pentingnya pemahaman topik ini.
Seringnya terjadi CCO dalam suatu proyek dapat menjadi indikasi adanya perencanaan awal yang kurang matang, lingkup kerja yang tidak terdefinisi dengan baik sejak awal, atau investigasi kondisi lapangan yang tidak memadai. Sebagaimana dicatat dalam 35, “CCO yang sering dapat berdampak negatif pada waktu, biaya, produktivitas, tingkat risiko, dan hubungan antar pihak dalam proyek.” Jika desain awal sudah matang dan komprehensif, serta investigasi lapangan dilakukan secara menyeluruh, idealnya kebutuhan akan CCO selama masa pelaksanaan dapat diminimalkan. Banyaknya CCO seringkali menunjukkan adanya kekurangan dalam tahap perencanaan atau ketidakmampuan untuk mengantisipasi berbagai kondisi lapangan secara akurat.35 Oleh karena itu, upaya maksimal harus difokuskan pada tahap perencanaan dan desain untuk mengurangi potensi perubahan selama pelaksanaan. Namun, jika perubahan memang tidak dapat dihindari, maka proses CCO harus dijalankan secara transparan, adil, terdokumentasi dengan baik, dan secepat mungkin untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap proyek.
Penting juga untuk memahami perbedaan terminologi yang kadang digunakan secara bergantian namun memiliki nuansa makna yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam 35, Contract Change Order (CCO) pada dasarnya adalah permintaan atau usulan untuk melakukan perubahan terhadap kontrak. Jika usulan perubahan tersebut disetujui, maka formalisasinya ke dalam dokumen kontrak yang mengikat secara hukum biasanya dilakukan melalui suatu Addendum kontrak. Addendum secara fisik merupakan tambahan atau perubahan terhadap klausul-klausul kontrak yang sudah ada dan secara hukum melekat pada perjanjian utama. Istilah Amendment lebih sering merujuk pada perubahan yang bersifat administratif atau koreksi minor tanpa mengubah substansi utama kontrak. Pemahaman yang benar terhadap terminologi ini penting untuk memastikan kejelasan hukum dalam setiap dokumentasi perubahan kontrak.
6.4. Proses Serah Terima Pekerjaan: Provisional Handover (PHO) dan Final Handover (FHO)
Proses serah terima pekerjaan merupakan tonggak penting yang menandai penyelesaian tahapan-tahapan krusial dalam proyek konstruksi dan melibatkan pengalihan tanggung jawab dari Penyedia Jasa (Kontraktor) kepada Pengguna Jasa. Terdapat dua tahap utama dalam serah terima pekerjaan, yaitu Serah Terima Pertama atau Sementara (Provisional Hand Over – PHO) dan Serah Terima Akhir (Final Hand Over – FHO).
- Serah Terima Pertama/Sementara (Provisional Hand Over – PHO): PHO, yang dalam diagram tahapan kontrak di Modul 1 disebut sebagai penerbitan Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1) 3, dilakukan setelah seluruh pekerjaan fisik utama yang tercantum dalam kontrak telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor secara substansial dan telah lulus dari serangkaian pengujian fungsi dan komisioning (jika dipersyaratkan).33
Proses PHO umumnya melibatkan beberapa langkah berikut 33:
- Pemberitahuan Kesiapan PHO: Kontraktor secara resmi memberitahukan kepada Pengguna Jasa (atau wakilnya, yaitu Konsultan Pengawas) bahwa pekerjaan telah siap untuk diserahterimakan. Pemberitahuan ini biasanya disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan penyelesaian pekerjaan, hasil pengujian, dan gambar terbangun (as-built drawings).
- Inspeksi Bersama: Tim dari pihak Pengguna Jasa dan Kontraktor (seringkali didampingi oleh Konsultan Pengawas) melakukan inspeksi atau pemeriksaan bersama terhadap seluruh hasil pekerjaan di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, gambar rencana, dan standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak.
- Pembuatan Daftar Cacat/Kekurangan (Punch List / Defect List): Jika selama inspeksi bersama ditemukan adanya pekerjaan yang belum sempurna, cacat minor, atau kekurangan-kekurangan lain yang tidak mempengaruhi fungsi utama bangunan secara signifikan, maka akan dibuatkan daftar cacat atau punch list.33 Daftar ini mencatat semua item yang perlu diperbaiki atau disempurnakan oleh Kontraktor.
- Perbaikan oleh Kontraktor: Kontraktor berkewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap semua item yang tercantum dalam punch list dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- Verifikasi Perbaikan: Setelah Kontraktor menyatakan telah menyelesaikan perbaikan, dilakukan inspeksi ulang atau verifikasi untuk memastikan bahwa semua item dalam punch list telah diperbaiki dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan.
- Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama: Jika semua hasil pekerjaan telah dinilai memenuhi syarat dan semua item punch list (jika ada) telah diperbaiki dengan memuaskan, maka diterbitkanlah Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) atau dokumen PHO. Dokumen ini ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses PHO, sebagaimana tercantum dalam standar format administrasi proyek 30, meliputi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima I (Pertama), Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama), Daftar Periksa (Checklist) Hasil Pemeriksaan Pekerjaan I (Pertama), dokumentasi visual (foto/video) hasil pemeriksaan, Surat Undangan dan Surat Perintah Pemeriksaan Pekerjaan, Permohonan Pemeriksaan Tahap I dari Kontraktor, serta Berita Acara Opname Lapangan yang mencatat Defect List beserta checklist-nya.Setelah PHO dilaksanakan dan BAST 1 diterbitkan, dimulailah periode yang disebut Masa Pemeliharaan (Maintenance Period atau Defect Liability Period).33 Selama periode ini, Kontraktor masih memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki setiap cacat mutu atau kerusakan yang mungkin timbul pada hasil pekerjaan, yang bukan disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau faktor eksternal di luar kendali Kontraktor.
- Masa Pemeliharaan (Maintenance Period / Defect Liability Period): Jangka waktu Masa Pemeliharaan biasanya ditetapkan dalam kontrak (umumnya berkisar antara 6 bulan hingga 1 atau 2 tahun, tergantung kompleksitas proyek). Selama periode ini, Pengguna Jasa akan mengoperasikan atau memanfaatkan hasil pekerjaan, dan jika ditemukan adanya cacat atau kerusakan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor, maka Kontraktor wajib melakukan perbaikan tanpa adanya biaya tambahan bagi Pengguna Jasa.33
- Serah Terima Akhir (Final Hand Over – FHO): FHO, yang dalam Modul 1 disebut sebagai penerbitan Berita Acara Serah Terima 2 (BAST 2) 3, dilakukan setelah Masa Pemeliharaan berakhir dan setelah Kontraktor menyelesaikan semua kewajiban perbaikan atas cacat mutu yang teridentifikasi selama Masa Pemeliharaan (jika ada) dengan baik dan diterima oleh Pengguna Jasa.34 Dengan dilaksanakannya FHO, proyek dianggap telah selesai secara definitif, dan seluruh tanggung jawab atas hasil pekerjaan sepenuhnya beralih kepada Pengguna Jasa. Pada tahap ini juga biasanya dilakukan pengembalian sisa retensi pembayaran (jika ada) dan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada Kontraktor.3
Penyusunan punch list yang detail, jelas, dan disepakati bersama pada saat PHO memegang peranan kunci untuk memastikan bahwa semua kekurangan atau cacat minor dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum FHO. Ketidakjelasan atau ketidaksepakatan mengenai item-item yang tercantum dalam punch list dapat memperpanjang proses penyelesaian, menimbulkan friksi antara para pihak, dan menghambat tercapainya FHO secara tepat waktu. Oleh karena itu, proses inspeksi bersama untuk PHO harus dilakukan secara teliti dan profesional oleh tim yang kompeten dari kedua belah pihak. Setiap item yang masuk dalam punch list harus dideskripsikan dengan jelas, terukur (jika memungkinkan), dan memiliki target waktu perbaikan yang disepakati.
Selama Masa Pemeliharaan, jika Kontraktor gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajiban perbaikannya terhadap cacat mutu yang timbul, Pengguna Jasa umumnya memiliki hak kontraktual untuk menggunakan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond), jika ada, atau melakukan perbaikan tersebut dengan menunjuk pihak ketiga dan membebankan seluruh biayanya kepada Kontraktor. Untuk itu, Kontraktor harus senantiasa mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk dapat merespons dan menangani setiap pemberitahuan cacat mutu dari Pengguna Jasa secara cepat dan tuntas selama Masa Pemeliharaan. Di sisi lain, Pengguna Jasa juga perlu aktif dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan dan segera melaporkan secara resmi setiap cacat yang teridentifikasi kepada Kontraktor.
Berikut adalah tabel yang merangkum berbagai jenis dokumen administrasi kunci yang relevan pada setiap tahapan proyek konstruksi:
Tabel 6.1: Ringkasan Dokumen Administrasi Kunci per Tahapan Proyek Konstruksi
| Tahapan Proyek | Nama Dokumen Kunci (Contoh dari ) | Tujuan Singkat Dokumen |
| Pra-Konstruksi / PCM | Surat Undangan Rapat PCM, Risalah Rapat PCM, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK/RK3K), Rencana Mutu Kontrak (RMK) | Menyatukan persepsi awal, menyepakati rencana dasar pelaksanaan, keselamatan, dan mutu. |
| Awal Pelaksanaan / MC0 | Surat Perintah Pengukuran, Berita Acara Pengukuran Lapangan Bersama, Rincian Indikasi Perubahan MC0, Master Schedule MC0 | Memverifikasi kondisi lapangan awal, menyesuaikan volume/desain jika perlu, memutakhirkan jadwal. |
| Selama Pelaksanaan | Instruksi Harian, Izin Kerja, Pengajuan Material & Persetujuan, Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan, Bulanan) | Mencatat arahan, mengontrol pekerjaan berisiko, memastikan kualitas material, memantau progres & kinerja. |
| Perubahan Kontrak / CCO | Surat Perjanjian Addendum, SK Pekerjaan Tambah Kurang, BA Evaluasi & Negosiasi, RAB Addendum, Jadwal Addendum | Meresmikan perubahan lingkup, biaya, atau waktu kontrak secara hukum. |
| Serah Terima Pertama / PHO | Permohonan Pemeriksaan, BA Pemeriksaan I, BA Serah Terima I, Checklist Hasil Pemeriksaan, BA Opname Lapangan Defect List | Memeriksa penyelesaian pekerjaan, mencatat cacat/kekurangan, serah terima sementara pekerjaan, memulai masa pemeliharaan. |
| Serah Terima Akhir / FHO | Permohonan Pemeriksaan Akhir, BA Pemeriksaan Akhir, BA Serah Terima Akhir | Memastikan semua cacat telah diperbaiki, serah terima final pekerjaan, mengakhiri tanggung jawab kontraktor (kecuali garansi laten). |
Tabel ini memberikan gambaran visual yang sistematis mengenai jenis-jenis dokumen administrasi yang esensial pada setiap fase kritis dalam siklus hidup proyek konstruksi. Pemahaman ini akan membantu mahasiswa dalam mengorganisir pengetahuan mereka mengenai alur kerja administratif dan menyadari betapa pentingnya setiap dokumen tersebut. Hal ini sangat relevan mengingat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini secara spesifik menyebutkan berbagai kasus administrasi (seperti administrasi pembebasan lahan, administrasi mulainya pekerjaan, administrasi perintah perubahan, dan administrasi pelaporan) yang kesemuanya memerlukan dokumentasi yang spesifik dan akurat.3
BAB VII: PENGANTAR MANAJEMEN RISIKO DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI
Proyek konstruksi secara inheren mengandung berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif dan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial dalam administrasi kontrak konstruksi.
7.1. Identifikasi Risiko Umum dalam Kontrak Konstruksi
Risiko dalam proyek konstruksi dapat bersumber dari berbagai aspek dan memiliki dampak yang bervariasi. Beberapa risiko umum yang sering dihadapi antara lain:
- Risiko Hukum: Timbul dari penyusunan kontrak yang kurang optimal, penggunaan bahasa hukum yang ambigu, klausul yang tidak mencakup potensi perubahan kondisi lapangan, atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.22 Risiko ini juga mencakup potensi kontrak menjadi tidak sah secara hukum, timbulnya celah hukum yang dapat dieksploitasi dalam penyelesaian sengketa, terhambatnya proses pembayaran, dan terganggunya kelancaran pelaksanaan proyek secara keseluruhan akibat ketidakpastian hukum.29
- Risiko Teknis: Berkaitan dengan aspek desain, metode pelaksanaan, kondisi geoteknik atau kondisi lapangan lain yang tidak terduga, serta ketersediaan dan kualitas material atau peralatan.
- Risiko Finansial: Meliputi risiko kenaikan harga material, fluktuasi nilai tukar mata uang (untuk proyek dengan komponen impor), kesulitan pendanaan dari pihak Pengguna Jasa, atau keterlambatan pembayaran kepada Penyedia Jasa.
- Risiko Terkait Perubahan Kontrak (CCO): Sebagaimana telah dibahas, perubahan kontrak yang sering terjadi atau dikelola dengan buruk dapat menimbulkan dampak negatif pada jadwal penyelesaian proyek (keterlambatan), peningkatan biaya pelaksanaan, penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan tingkat risiko secara keseluruhan, dan bahkan dapat merusak hubungan kerja antar para pihak.35
- Risiko Eksternal: Seperti perubahan peraturan pemerintah, masalah perizinan, kondisi cuaca ekstrem, bencana alam, atau isu sosial politik di sekitar lokasi proyek.
Identifikasi risiko secara komprehensif dan alokasi tanggung jawab atas risiko tersebut secara adil dan jelas di dalam kontrak merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen risiko. Proses manajemen risiko idealnya dimulai sejak tahap perencanaan awal proyek dan terus berlanjut selama siklus hidup proyek.
Penting untuk disadari bahwa banyak risiko dalam proyek konstruksi seringkali saling terkait dan dapat memicu efek berantai. Sebagai contoh, risiko desain yang buruk atau tidak lengkap (sebuah risiko teknis) dapat secara langsung menyebabkan perlunya perubahan pekerjaan yang signifikan selama masa pelaksanaan (memicu CCO). Perubahan pekerjaan ini kemudian dapat meningkatkan risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian jadwal proyek. Pada akhirnya, jika dampak dari perubahan ini tidak dapat dikelola atau disepakati dengan baik oleh para pihak, maka dapat meningkat menjadi risiko timbulnya klaim dan sengketa.22 Adanya efek domino semacam ini menunjukkan bahwa pendekatan manajemen risiko yang bersifat parsial atau terisolasi seringkali tidak efektif. Diperlukan suatu pendekatan manajemen risiko yang holistik dan terintegrasi, yang mampu melihat keterkaitan antar berbagai jenis risiko dan dampaknya secara keseluruhan terhadap proyek.
7.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, Litigasi)
Meskipun upaya pencegahan sengketa melalui administrasi kontrak yang baik dan manajemen risiko yang proaktif sangat diutamakan, potensi timbulnya perselisihan dalam proyek konstruksi yang kompleks tetap ada. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat penting.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 88, mengatur mengenai tahapan dan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi.8 Secara umum, UUJK No. 2/2017 mendorong penyelesaian sengketa secara bertahap, dengan mengedepankan upaya-upaya damai terlebih dahulu:
- Musyawarah untuk Mufakat: Tahap pertama yang wajib diupayakan oleh para pihak yang bersengketa adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama.
- Penyelesaian di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution – ADR): Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti:
- Mediasi: Proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.
- Konsiliasi: Serupa dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian kepada para pihak.
- Arbitrase: Penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak (atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase), yang keputusannya bersifat final dan mengikat (final and binding).
- Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi): Jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau tidak dipilih, para pihak dapat membawa sengketa mereka ke pengadilan negeri untuk diselesaikan melalui proses litigasi.
Penting untuk dicatat bahwa pilihan mekanisme penyelesaian sengketa (selain musyawarah yang bersifat wajib sebagai tahap awal) idealnya telah dicantumkan secara jelas dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Jika kontrak tidak mengatur mengenai hal ini, maka para pihak yang bersengketa perlu membuat persetujuan tertulis tersendiri mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh.8
Landasan hukum utama untuk arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.15 UU ini mendefinisikan Arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1).15 Perjanjian Arbitrase dapat berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian pokok atau berupa perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3).15 UU ini juga mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10).15 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut UU ini adalah sengketa di bidang perdagangan (yang mencakup jasa konstruksi) dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 5 ayat 1).15 Namun, sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (Pasal 5 ayat 2).15
Selain mekanisme formal tersebut, dalam praktik penyelesaian klaim atau sengketa tahap awal, metode seperti Engineering Judgement (keputusan berdasarkan penilaian teknis oleh Enjinir), Negosiasi langsung antar para pihak, penggunaan Dispute Review Board (Dewan Sengketa yang dibentuk sejak awal proyek), atau bahkan Mini-trial juga dikenal dan terkadang digunakan.26 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini juga mengindikasikan adanya pembahasan mendalam mengenai “Kasus Manajemen Sengketa (Dispute Management)” pada minggu-minggu akhir perkuliahan.3
Meskipun UU No. 2 Tahun 2017 menyediakan beragam opsi penyelesaian sengketa, efektivitas dari masing-masing mekanisme tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemauan dan itikad baik dari para pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses penyelesaian, serta kualitas dan kejelasan klausul penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Musyawarah, sebagai contoh, hanya akan berhasil jika kedua belah pihak memiliki niat tulus untuk mencari solusi bersama.8 Mediasi memerlukan peran mediator yang netral dan kompeten, serta kesediaan para pihak untuk melakukan kompromi. Arbitrase memerlukan adanya perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat. Jika klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dirumuskan secara ambigu, atau jika salah satu pihak tidak kooperatif, maka proses penyelesaian sengketa dapat terhambat meskipun telah ada payung hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, perancangan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, pemilihan mekanisme yang paling sesuai dengan potensi karakteristik sengketa proyek, dan jika memungkinkan, penggunaan mekanisme pencegahan sengketa seperti Dewan Sengketa (Dispute Adjudication Board atau Dispute Resolution Board) sejak awal proyek, menjadi sangat penting.
Penggunaan “Engineering Judgement” sebagai salah satu metode awal penyelesaian klaim yang disebut sering digunakan 26 menunjukkan peran sentral Konsultan atau Enjinir dalam tahap awal penyelesaian perbedaan pendapat. Jika Konsultan Desain atau Pengawas (yang bertindak sebagai Enjinir) dapat mengambil keputusan akhir yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka ini bisa menjadi cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah.26 Namun, perlu disadari bahwa peran ganda Enjinir (sebagai wakil Pengguna Jasa sekaligus sebagai penentu yang diharapkan imparsial) dapat menjadi sumber potensi sengketa lebih lanjut jika keputusannya dianggap tidak adil atau memihak. Jika pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Enjinir menganggap bahwa Enjinir tidak bertindak secara imparsial (misalnya karena Enjinir dibayar oleh Pengguna Jasa), mereka kemungkinan akan menolak keputusan tersebut dan memilih untuk melanjutkan sengketa ke mekanisme penyelesaian yang lebih formal. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dalam kontrak mengenai sejauh mana keputusan Enjinir bersifat final dan mengikat, dan dalam kondisi apa para pihak dapat beralih ke mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang lebih independen.
BAB VIII: PENGENALAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN (SMKK)
Penyelenggaraan proyek konstruksi modern tidak hanya dituntut untuk menghasilkan bangunan yang berkualitas secara teknis dan ekonomis, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, kerangka kerja untuk aspek-aspek ini diatur melalui Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK).
8.1. Pentingnya SMKK dalam Proyek Konstruksi
UUJK No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK) sebagai “pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”.8 Lebih lanjut, Pasal 59 UUJK No. 2/2017 secara tegas mewajibkan bahwa “Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan”.8
Kewajiban penerapan SMKK ini dipertegas dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.38 Peraturan Menteri ini menggantikan regulasi sebelumnya (Permen PUPR No. 21/2019) dan mencakup aspek penjaminan mutu serta pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari SMKK. Tujuan utama dari penerapan SMKK adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di setiap tahapan proyek, dengan sasaran akhir untuk mencapai kondisi tanpa kecelakaan kerja (zero accident) dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.40
Penerapan SMKK bukan lagi merupakan suatu pilihan atau praktik terbaik semata, melainkan telah menjadi suatu kewajiban hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan SMKK dapat dikenai sanksi administratif dan bahkan dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum jika terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan bangunan. Penekanan pada SMKK ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam industri konstruksi menuju praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan mengutamakan kesejahteraan serta keselamatan tenaga kerja.
8.2. Tanggung Jawab Para Pihak terkait SMKK dan Dokumentasi Terkait
Tanggung jawab untuk menerapkan SMKK tidak hanya dibebankan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor), melainkan terdistribusi di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. UUJK No. 2 Tahun 2017 Pasal 60 secara jelas menyatakan bahwa Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya SMKK.8
Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 38 mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan penerapan SMKK dan tanggung jawab masing-masing pihak:
- Tahap Pengkajian dan Perencanaan: Pada tahap ini, Pengguna Jasa bertanggung jawab untuk menyusun Rancangan Konseptual SMKK, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengkajian atau Konsultan Perencanaan. Rancangan ini berisi data umum proyek serta identifikasi awal aspek keselamatan konstruksi, deskripsi risiko, dan rekomendasi teknis.
- Tahap Perancangan: Konsultan Perencana bertugas untuk mengembangkan detail SMKK berdasarkan rancangan konseptual, yang akan menjadi bagian dari dokumen desain.
- Tahap Persiapan Pengadaan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil Pengguna Jasa memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi bahaya Keselamatan Konstruksi dan menetapkan tingkat risiko pekerjaan konstruksi. Proses ini dapat mengacu pada hasil dokumen perancangan dan dapat melibatkan konsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
- Tahap Pelaksanaan: Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang detail. RKK ini kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa (atau wakilnya) pada saat Rapat Pra-Konstruksi (PCM). Pengendalian pelaksanaan RKK di lapangan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk persyaratan dalam pengajuan izin mulai kerja, analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis – JSA), dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan (Method Statement).
- Tahap Pengawasan: Konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) juga wajib menyusun RKK Pengawasan yang berisi rencana bagaimana mereka akan mengawasi penerapan SMKK oleh Kontraktor.
Dokumentasi terkait SMKK memegang peranan yang sangat penting, baik untuk perencanaan, implementasi, pemantauan, maupun sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa dokumen kunci SMKK meliputi Rancangan Konseptual SMKK, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disusun oleh Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas, Program Mutu, Job Safety Analysis (JSA), Method Statement, laporan pelaksanaan SMKK secara berkala, formulir izin kerja, daftar periksa (checklist) inspeksi keselamatan, dan lain-lain.30
Implementasi SMKK yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, bukan hanya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa semata. Pengguna Jasa memiliki peran krusial dalam tahap perencanaan, termasuk memastikan bahwa aspek SMKK telah dipertimbangkan dalam desain dan penganggaran proyek. Konsultan Pengawas bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi SMKK di lapangan. Sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10/2021, tugas dan tanggung jawab para pihak, termasuk PPK dalam menyusun spesifikasi teknis yang telah mempertimbangkan SMKK, dan Konsultan Pengawas dalam mengawasi penerapannya, telah dirinci dengan jelas.40 Dengan demikian, SMKK harus menjadi bagian integral dari budaya kerja di setiap proyek konstruksi, yang didukung oleh kebijakan yang jelas, pelatihan yang memadai bagi seluruh personil, alokasi sumber daya yang cukup, dan sistem pengawasan yang efektif dari semua tingkatan manajemen.
Salah satu aspek penting dalam keberhasilan penerapan SMKK adalah pengalokasian anggaran yang memadai. Biaya untuk implementasi SMKK, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, pemasangan rambu-rambu, hingga penyediaan fasilitas kesehatan darurat, harus diperhitungkan sejak tahap awal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pengguna Jasa dan juga harus dimasukkan secara realistis dalam penawaran harga oleh Penyedia Jasa. Kegagalan dalam mengalokasikan anggaran yang cukup seringkali menjadi kendala utama dalam implementasi SMKK di lapangan.41 Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No. 68 Tahun 2024, yang dirujuk dalam 41, bahkan telah mengatur mengenai tata cara penyusunan perkiraan biaya Pekerjaan Konstruksi yang harus mencakup komponen biaya SMKK. Hal ini menunjukkan bahwa aspek biaya merupakan faktor determinan yang tidak dapat diabaikan.
Meskipun telah ada pedoman SMKK yang komprehensif, tantangan dalam implementasi di lapangan masih sering ditemui. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah minimnya pemahaman mengenai manfaat SMKK dari sebagian pelaku konstruksi, pengawasan yang belum optimal, keterbatasan anggaran yang dialokasikan, serta jumlah petugas keselamatan konstruksi yang bersertifikat yang masih minim.41 Adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan praktik di lapangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, asosiasi industri jasa konstruksi, dan institusi pendidikan untuk terus melakukan sosialisasi, menyelenggarakan pelatihan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keselamatan konstruksi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap SMKK di seluruh rantai pasok industri konstruksi di Indonesia.
BAB IX: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Analisis komprehensif terhadap aspek hukum dan administrasi kontrak konstruksi di Indonesia, sebagaimana dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, menghasilkan beberapa kesimpulan penting:
- Dasar Hukum yang Berlapis: Kontrak konstruksi di Indonesia berlandaskan pada KUHPerdata sebagai hukum umum perjanjian, yang kemudian diperkuat dan dikhususkan oleh UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksananya, PP No. 22 Tahun 2020. Pemahaman integratif terhadap berbagai tingkatan regulasi ini esensial bagi para praktisi. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan akibat hukumnya menurut Pasal 1338 KUHPerdata tetap menjadi fondasi utama.
- Kompleksitas Kontrak Konstruksi: Kontrak konstruksi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kontrak komersial lain, meliputi durasi panjang, keterlibatan multi-pihak, risiko tinggi, dan ketergantungan pada “keseluruhan dokumen kontrak” yang mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif.
- Peran Kunci Para Pihak: Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana), dan Penyedia Jasa Konsultansi (Enjinir/Pengawas/Manajemen Konstruksi) memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang spesifik. Meskipun hubungan kontraktual utama terjalin antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, peran Enjinir sebagai wakil Pengguna Jasa sangat signifikan dan seringkali menentukan dinamika proyek.
- Administrasi Kontrak sebagai Fungsi Strategis: Administrasi kontrak bukan sekadar kegiatan klerikal, melainkan fungsi manajemen yang vital untuk memastikan pemenuhan kewajiban kontraktual, pengelolaan risiko, pencapaian tujuan proyek, dan pencegahan sengketa. Perspektif administrasi proyek berbeda bagi masing-masing pihak, namun memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif.
- Pentingnya Terminologi dan Dokumentasi: Pemahaman akurat terhadap terminologi kunci (persyaratan kontrak, strategi, klaim, sengketa) dan pengelolaan dokumentasi yang cermat pada setiap tahapan siklus hidup kontrak (PCM, MC0, CCO, PHO, FHO, laporan rutin) adalah fundamental untuk menghindari kesalahpahaman, memfasilitasi manajemen perubahan, dan menyediakan bukti jika terjadi klaim atau sengketa.
- Manajemen Risiko dan Penyelesaian Sengketa: Proyek konstruksi sarat akan risiko. Identifikasi risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas (musyawarah, mediasi, arbitrase, litigasi) harus diatur dalam kontrak. Ambiguitas kontrak dan kegagalan mengikuti prosedur pemberitahuan klaim adalah pemicu umum sengketa.
- Kewajiban Penerapan SMKK: Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SMKK) merupakan kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Penerapan SMKK yang efektif memerlukan komitmen, anggaran, kompetensi, dan dokumentasi yang memadai.
Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan, khususnya bagi mahasiswa Magister Teknik Sipil yang sedang mendalami mata kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak:
- Penguatan Pemahaman Holistik: Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis konstruksi, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum, prinsip-prinsip administrasi kontrak, dan dinamika hubungan antar para pihak.
- Fokus pada Penyusunan Kontrak yang Berkualitas: Mengingat ambiguitas kontrak sering menjadi sumber masalah, mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk menganalisis dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen kontrak yang jelas, komprehensif, adil, dan minim risiko interpretasi ganda. Perhatian khusus pada klausul hierarki dokumen, lingkup kerja, alokasi risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat dianjurkan.
- Pengembangan Keterampilan Manajemen Klaim dan Sengketa: Mahasiswa perlu memahami prosedur pengajuan dan penanganan klaim secara benar, serta strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Studi kasus mengenai klaim dan sengketa aktual dapat memperkaya pemahaman.
- Internalisasi Prinsip SMKK: Aspek SMKK harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mahasiswa perlu memahami tanggung jawab masing-masing pihak terkait SMKK dan pentingnya integrasi SMKK dalam seluruh siklus proyek.
- Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi Kontrak: Mengingat kompleksitas administrasi dan dokumentasi, mahasiswa sebaiknya diperkenalkan dengan perkembangan teknologi dan perangkat lunak yang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas administrasi kontrak konstruksi.
- Studi Lanjutan dan Praktik Terbaik: Mendorong mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru, standar industri (seperti FIDIC), dan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam administrasi kontrak dan manajemen proyek konstruksi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum dan administrasi kontrak, lulusan Magister Teknik Sipil diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan profesionalisme industri jasa konstruksi di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Hardjomuljadi, S. (2023). Modul 1: Kontrak Konstruksi dan Administrasi Proyek. Universitas Mercu Buana. 3
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. 3
- Silabus Mata Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. 3
- Berbagai sumber artikel dan jurnal yang dirujuk dalam analisis (misalnya1).
Referensi Online
- jateng.bpk.go.id, accessed May 22, 2025, https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf
- pengertian dan ruang lingkup hukum kontrak konstruksi – Sriwijaya University Repository, accessed May 22, 2025, https://repository.unsri.ac.id/100784/1/Full%20Buku%20Kontrak%20Meria%20Utama%20Cetakan%201.pdf
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana.
- Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang – SIP Law Firm, accessed May 22, 2025, https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id
- 4 Syarat Sah Kontrak dalam Hukum – detikcom, accessed May 22, 2025, https://www.detik.com/sumut/berita/d-7492216/4-syarat-sah-kontrak-dalam-hukum
- Regulasi Hukum Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Legal Regulation of Contracts on Co, accessed May 22, 2025, https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/2103/pdf
- PERATURAN ARTIKEL PEMBATASAN ASAS “FREEDOM OF CONTRACT” DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL – Pengadilan Negeri Banda Aceh, accessed May 22, 2025, https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/
- peraturan.bpk.go.id, accessed May 22, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/26731/UU%20No%202%20Tahun%202017.pdf
- UU02-2017.pdf – JDIH, accessed May 22, 2025, https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/UU/2017/01/UU02-2017.pdf
- kontrak kerja konstruksi – antara hukum privat dan hukum publik – UNG REPOSITORY, accessed May 22, 2025, https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/6584/Mutia-Cherawaty-Thalib-Kontrak-Kerja-Konstruksi-Antara-Hukum-Privat-dan-Hukum-Publik.pdf
- lib.ui.ac.id, accessed May 22, 2025, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old18/129532-T%2026678-Tinjauan%20yuridis%20mengenai-Metodologi.pdf
- PENGETAHUAN DASAR KONTRAK KONSTRUKSI PELATIHAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI – SiMANTU, accessed May 22, 2025, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/4e50d_319549Modul_02_-_Pengetahuan_Dasar_Kontrak_Konstruksi.pdf
- peraturan.bpk.go.id, accessed May 22, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/128474/PP%20Nomor%2022%20Tahun%202020.pdf
- mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menurut – IBLAM LAW REVIEW, accessed May 22, 2025, https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/32/30/118
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA – UU301999.pdf – Regulasip, accessed May 22, 2025, https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2018/November/5bf2875d95857/UU301999.pdf
- ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999, accessed May 22, 2025, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=498834&val=10222&title=ARBITRASE+SEBAGAI+LEMBAGA+PENYELESAIAN+SENGKETA+MENURUT+UNDANG-UNDANG+NO+30+TAHUN+1999
- PP No. 22 Tahun 2020 – Peraturan BPK, accessed May 22, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020
- Administrasi Kontrak Konstruksi | PDF – Scribd, accessed May 22, 2025, https://id.scribd.com/doc/309018788/ADMINISTRASI-KONTRAK-KONSTRUKSI
- FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA KONSTRUKSI PADA PROYEK EPC BROWNFIELD – Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, accessed May 22, 2025, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/download/9321/6488
- 9 pemerintah Nomor 22 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi – LPSE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, accessed May 22, 2025, https://lpse.kaltaraprov.go.id/eproc4/dl/1497cafd721074525b74d9b9369d103e42a4169b563f6bc9f76664ae92f00fadbf2c11c26ec2c1178172f848747eb01e7cf3778c5a84d0eef92b55891b13a1f335f0de9cfc0af8b6f510ced0867c7cb7cb9a33dbd0218fcd611d7ca8cdb2b8c5
- KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN – LPSE PUPR, accessed May 22, 2025, https://lpse.pu.go.id/eproc4/dl/abc9d00df7b80f0374c5a1ebb9b5fc81e11d190c2c56487a08c9ccba84099f00ed93f3b5463d6eefe6a472abb7824a11c963d729123600065cf133d79c20354b654d042fd05e9a8cdc126b6f5cb4faf1ef287e41527a144fd8c3e0a66a7eb4ba7b7df17c858724bf50a0909c779f2c1c
- Peran Administrasi Kontrak dalam Mengelola Risiko Hukum pada …, accessed May 22, 2025, https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4120
- KMS:: Pengendalian Pelaksanaan Kontrak, accessed May 22, 2025, https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengendalian-pelaksanaan-kontrak-8a4e0c0d/detail/
- 8 Tahapan Penyusunan Kontrak (Contract Formation) dalam Proyek Konstruksi, accessed May 22, 2025, https://diklatpemerintah.id/8-tahapan-penyusunan-kontrak-contract-formation-dalam-proyek-konstruksi/
- Berikut 9 Tahap Penyusunan Kontrak untuk Proyek Konstruksi – ScaleOcean, accessed May 22, 2025, https://scaleocean.com/id/blog/industri/9-tahap-penyusunan-kontrak
- ced.petra.ac.id, accessed May 22, 2025, https://ced.petra.ac.id/index.php/civ/article/download/16285/16277/16283
- IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPOTENSI MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA PALANGKA RAYA, accessed May 22, 2025, https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JT/article/download/1309/1082
- Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 1999:UU RI no.30 th.1999 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, accessed May 22, 2025, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5792
- Apa Saja Isi Kontrak Kerja Konstruksi? | IZIN.co.id Blog, accessed May 22, 2025, https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2025/04/24/kontrak-kerja-konstruksi-harus-mencakup-apa-saja/
- Standar Format Administrasi Proyek (Final) PDF | PDF | Bisnis …, accessed May 22, 2025, https://id.scribd.com/document/355017674/STANDAR-FORMAT-ADMINISTRASI-PROYEK-FINAL-pdf
- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE CONSTRUCTION MEETING) SOP/UPM/DJBM-89 Revisi 01 TAHUN 202, accessed May 22, 2025, https://binamarga.pu.go.id/index.php/peraturan/dokumen/sopupmdjbm-89-revisi-01-tentang-rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pre-construction-meeting
- Berikut Tugas Administrasi Proyek dan Dokumen yang Dikelola – ScaleOcean, accessed May 22, 2025, https://scaleocean.com/id/blog/industri/tugas-administrasi-proyek
- Provisional Hand Over (PHO) dalam Proyek Konstruksi: Pengertian, Proses, dan Pentingnya, accessed May 22, 2025, https://8thinktank.com/provisional-hand-over-pho/
- PHO Proyek adalah: Definisi, Prosedur & Manfaatnya – Total ERP, accessed May 22, 2025, https://www.total-erp.com/blog/apa-itu-pho-dalam-proyek-konstruksi/
- Contract Change Order | PDF – Scribd, accessed May 22, 2025, https://www.scribd.com/document/664465532/CONTRACT-CHANGE-ORDER
- identifikasi dampak contract change order terhadap biaya dan kualitas pada proyek gedung laboratorium teknik 2 institut teknologi sumatera, accessed May 22, 2025, https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009100089/21116058_20_215801.pdf
- Contract Change Order | PDF – Scribd, accessed May 22, 2025, https://id.scribd.com/document/664465532/CONTRACT-CHANGE-ORDER
- TUGAS AKHIR STUDI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI DI KOTA MAKASSAR (BERDA – Repository | Universitas Hasanuddin, accessed May 22, 2025, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5889/2/D011171533_skripsi%201-2.pdf
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 | PDF – Scribd, accessed May 22, 2025, https://id.scribd.com/document/523326666/03-Peraturan-Menteri-PUPR-Nomor-10-Tahun-2021
- 2022SEMenteriPUPR10.pdf – JDIH – Kementerian PUPR, accessed May 22, 2025, https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/SEMenteriPUPR/2022/05/2022SEMenteriPUPR10.pdf
- Penerapan SMKK: Menuju Konstruksi Zero Accident, accessed May 22, 2025, https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/penerapan-smkk-menuju-konstruksi-zero-accident/